Konten dari Pengguna
Membantah Argumen Ferry Irwandi Atas Filsafat
15 Juli 2025 19:23 WIB
·
waktu baca 5 menit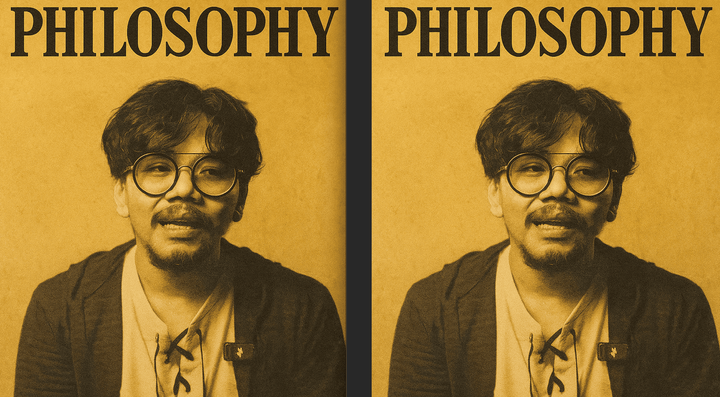
Kiriman Pengguna
Membantah Argumen Ferry Irwandi Atas Filsafat
Ferry ingin jurusan filsafat dihapus karena dianggap tak berguna. Padahal, filsafat penting untuk berpikir kritis, menggugat asumsi, dan jadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan modern.Abdan Sakura
Tulisan dari Abdan Sakura tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
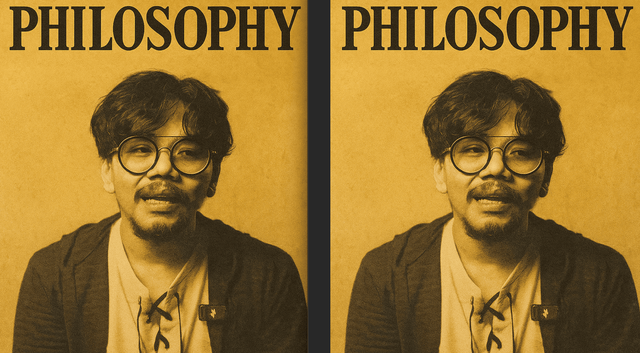
Pernyataan Ferry Irwandi di akun Instagram-nya pada 15 Juli yang menyerukan, “Jurusan filsafat dihapus saja!”, sekilas terdengar masuk akal. Banyak orang memang mengira bahwa filsafat tak berguna, tak membawa manfaat apa pun. Di telinga publik yang terbiasa menghitung segala sesuatu, ucapan semacam itu terasa wajar, bahkan seolah mewakili suara zaman.
Dalam video singkat itu, Ferry menyampaikannya dengan tenang, runtut, dan terdengar rasional. Menurutnya, teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Dulu, katanya, filsafat dibutuhkan karena ilmu belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Tapi kini, semua itu, sudah diambil alih oleh sains. Maka, filsafat tak lagi penting. Lebih baik dihapus saja.
Mari kita ambil jarak sejenak. Pendapat seperti yang disampaikan Ferry, bahwa jurusan filsafat sebaiknya dihapus, bukanlah hal baru. Banyak orang memikirkan hal serupa, dan saya sendiri telah mendengarnya berkali-kali. Bahkan beberapa kolega, teman dekat, hingga kerabat saya pernah melontarkan pertanyaan yang sama: Lulusan filsafat bisa kerja apa?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terdengar biasa saja, namun sesungguhnya mencerminkan cara masyarakat kita membingkai pandangan tentang pendidikan. Kita semakin terbiasa menilai ilmu dari seberapa cepat ia menghasilkan sesuatu. Jika manfaat praktisnya tidak segera tampak, sebuah ilmu dengan cepat dianggap tak berguna, tidak layak dipelajari, apalagi diajarkan.
Barangkali begitulah cara Ferry memandang filsafat: seperti benda usang di gudang institusi akademik, sebuah meja tua yang dianggap tak lagi menunjang produktivitas, dan karena itu, pantas disingkirkan. Tapi Ferry tidak sendirian. Ia mewakili gejala zaman, sebuah generasi yang semakin terlatih menghargai segala yang bisa langsung dipakai, namun justru semakin bingung ketika diajak berpikir tentang makna, arah, dan tujuan.
Ketika filsafat ditimbang hanya berdasarkan “guna”, maka pertanyaan tentang “guna dari guna itu sendiri” tidak pernah sempat diajukan. Padahal, pada esensinya, literatur manapun menyebut: “Semua manusia, pada dasarnya, ingin tahu.” Bukan ingin berguna, bukan ingin menghasilkan, tetapi ingin tahu, dan dari sanalah filsafat lahir.
Sementara itu, Ferry tampak berusaha menyandarkan filsafat pada kebergunaan, relevansi, dan dampak. Namun barangkali yang luput disadarinya adalah: filsafat justru hadir untuk mempertanyakan makna dari kata-kata itu. Sebab filsafat tidak tunduk pada logika fungsi atau relevansi yang proporsional, ia tidak melayani kegunaan, melainkan membongkar cara kita memahami guna itu sendiri.
Lagi pula, kata kunci “kegunaan”, yang kini dijadikan tolok ukur segalanya, bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ia lahir dari sejarah panjang, ketika segala hal dipaksa masuk ke dalam tabel kebermanfaatan. Dalam tradisi Yunani, misalnya, yang kini sering kita maksud sebagai “nilai guna” dahulu dikenal sebagai arete, keutamaan dalam bertindak. Tapi makna itu telah bergeser jauh, dan kini menyempit menjadi sekadar peran, fungsi, bahkan profesi.
Dunia modern telah menakar definisi semacam itu ke dalam logika pragmatis, yang hanya mengakui nilai jika bisa diukur, dihitung, dan digunakan. Maka, ketika filsafat dianggap tak praktis dan disuruh enyah, itu bukan argumen, itu gejala zaman. Dan Ferry tidak sendirian.
Lebih jauh, kritik yang dilontarkan Ferry sepenuhnya bergerak dalam horizon mistake category. Ia memaksakan parameter teknis pada ranah yang secara ontologis berada di luar batas-batas teknis. Filsafat, sejak asal historis dan konseptualnya, tidak dirancang untuk menjawab tuntutan instrumental tentang fungsi dan kegunaan.
Filsafat tidak lahir dari rahim kebutuhan operasional, dan sejak mula tak pernah berniat menjelma menjadi alat. Ia lebih menyerupai cermin bening yang dipasang di depan bangunan kehidupan bersama, bukan untuk menilai kinerja, melainkan untuk memperlihatkan rupa. Maka menjadi keliru jika ada yang menagih “output” dari filsafat.
Kekeliruan serupa muncul ketika Ferry menyebut bahwa filsafat “dulunya penting” hanya karena ilmu belum berkembang, dan kini jadi tidak relevan karena sains dan teknologi telah maju. Pernyataan ini bukan sekadar ahistoris, tetapi juga naif secara intelektual.
Ferry gagal melihat bahwa setiap lompatan besar dalam sejarah pengetahuan justru dimulai dari keberanian untuk bertanya secara filosofis. Tanpa keberanian Thales mempertanyakan mitos, tak akan ada sains alam. Tanpa struktur logika Aristoteles, tak akan ada dasar berpikir ilmiah. Tanpa Descartes yang menggugat segalanya demi menemukan kepastian, tak akan ada fondasi bagi rasionalitas modern. Dan tanpa pergulatan Karl Popper dan Thomas Kuhn, kita takkan pernah paham bahwa ilmu bukan sekadar akumulasi data, tapi medan tarik-menarik antara dugaan, kritik, dan revolusi gagasan.
Jadi, ketika seseorang berkata filsafat sudah tak relevan karena sains sudah maju, lagi-lagi, yang terdengar sebenarnya bukan argumen, tapi kemalasan berpikir yang dibungkus dalam baju modernitas.
Karena itu, ketika Ferry menyebut filsafat sebagai sekadar tumpukan asumsi yang belum terbukti secara saintifik bukan hanya simplistik, tetapi menyesatkan . Itu seperti lupa bahwa sebelum ada “bukti”, harus ada kriteria tentang apa yang layak disebut “bukti”.
Betapapun presisi sebuah klaim ilmiah, ia tidak pernah lahir dalam ruang kosong. Ia berdiri di atas dasar-dasar berpikir yang sejak awal dibentuk oleh filsafat, tentang apa yang bisa kita ketahui, bagaimana kita membuktikan, dan mengapa kita perlu membuktikan.
Mungkin Ferry tidak tahu bahwa justifikasi saintifik tidak pernah netral. Ia selalu membawa asumsi tentang realitas, kebenaran, dan nilai, semua pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains itu sendiri. Dan di titik itulah filsafat bekerja, diam-diam menopang, tanpa perlu berisik mengklaim. Maka, ketika filsafat dituduh “tidak saintifik”, yang sebetulnya sedang terjadi adalah pelupaan terhadap fondasi yang memungkinkan sains berdiri tegak.
Terakhir, terkait tudingan Ferry bahwa mahasiswa filsafat tidak memiliki 'ground keilmuan', barangkali perlu diluruskan. Masalahnya bukan terletak pada filsafatnya, melainkan pada kutipan-kutipan bijak yang berseliweran di media sosial dan yang sering disalahartikan atau digunakan sembarangan, sehingga kerap berujung pada tuduhan tak berdasar terhadap cara berpikir mahasiswa filsafat.
Sebab filsafat, pada hakikatnya, tidak hadir untuk memberi jawaban-jawaban instan. Ia tidak menawarkan solusi cepat dalam balutan kata-kata indah.
Dalam konteks itulah, seruan Ferry untuk menghapus filsafat sebetulnya mencerminkan kemunduran cara berpikir. Bukan tanda zaman yang tercerahkan, tapi kemerosotan, tindakan serampangan yang tak punya kepekaan historis.
Di tengah arus zaman yang sibuk memuja kecepatan dan efisiensi, sebagian orang, sebut saja Ferry di antaranya—mungkin percaya bahwa dunia akan terus melaju selama roda ekonomi berputar, teknologi diperbarui, dan angka-angka pertumbuhan terus naik.
Namun dunia bukan sekadar soal gerak; ia membutuhkan arah. Dan arah tidak lahir dari kalkulasi atau nilai guna semata. Ia muncul dari jeda, dari keheningan yang memberi ruang bagi manusia untuk bertanya.
Refleksi adalah titik tolak dari kebijaksanaan. Tanpanya, kita hanyalah bagian dari mesin besar yang bergerak tanpa sadar, tanpa tujuan.

