Konten dari Pengguna
Esai Hasan Junus yang Melampaui Zaman
11 Januari 2026 3:47 WIB
·
waktu baca 6 menit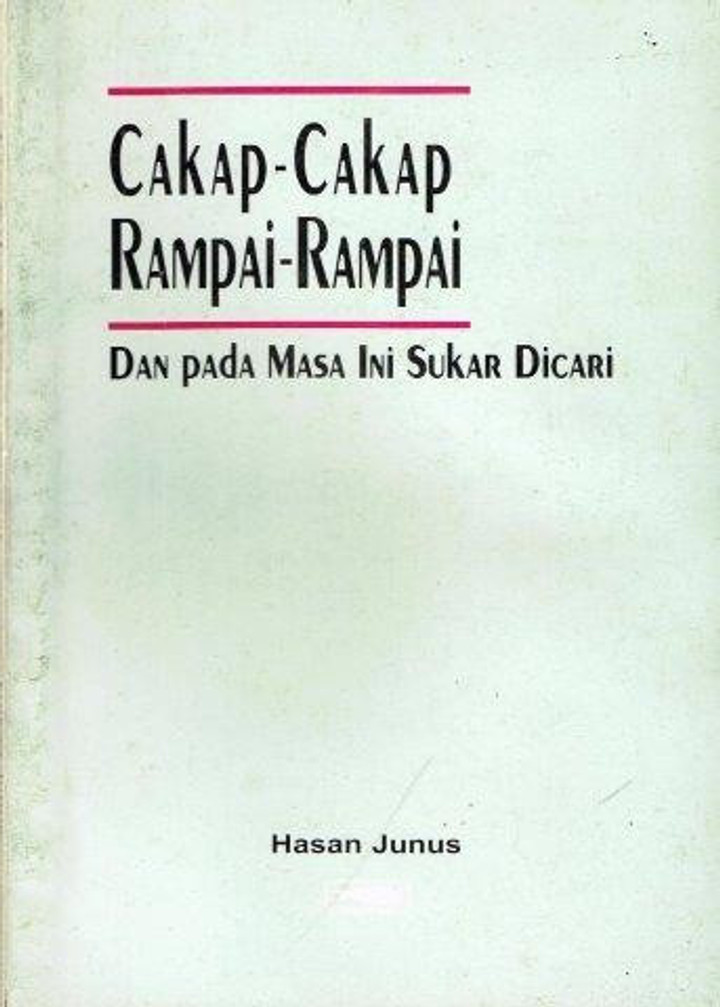
Kiriman Pengguna
Esai Hasan Junus yang Melampaui Zaman
Esai ini menelaah pemikiran Hasan Junus yang melampaui zamannya, dari seni dapur Melayu hingga Orang Pesukuan, sebagai cermin sejarah, identitas, dan kritik sosial masa kini.Dedi Arman
Tulisan dari Dedi Arman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
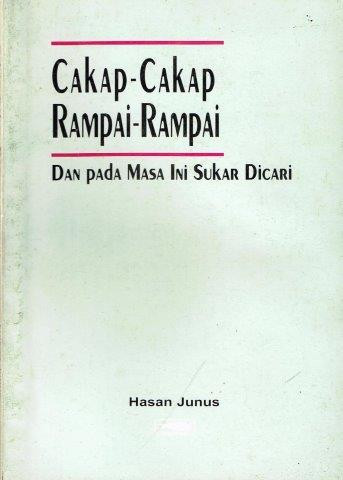
Nama Hasan Junus (1941–2012) menempati posisi istimewa dalam khazanah intelektual Kepulauan Riau. Hasan Junus (HJ) tipe manusia kompleks. Dapat dibaca sebagai sejarawan, antropolog, budayawan, sekaligus sastrawan. Sosoknya tidak pernah mengurung dirinya dalam sekat-sekat disiplin ilmu yang kaku. Ia menulis sejarah dengan cara yang berbeda: ringan, reflektif, dan sarat rasa. Sejarah baginya bukan sekadar paparan fakta dan tanggal, melainkan ruang permenungan tentang manusia, kebudayaan, dan makna hidup.
HJ sendiri pernah menyebut bahwa esai-esai sejarah yang ditulisnya bukanlah sejarah dengan syarat ilmiah yang ketat sebagaimana lazimnya karya akademik, lengkap dengan rujukan kaki dan metodologi formal. Esai-esainya lebih merupakan “makanan hati” daripada “makanan pikiran”. Rujukan dan referensi telah lebih dulu “lumat dikunyah”, menyatu dengan pikiran dan perasaan, lalu menjelma karya seni dalam bentuk esai. Inilah kekuatan HJ, menjembatani pengetahuan dan kepekaan, data dan rasa, sejarah dan kehidupan sehari-hari.
Dua esai Hasan Junus menunjukkan bagaimana gagasan-gagasannya melampaui zamannya. Dua esai tersebut adalah “Seni Dapur dan Raja Ali Haji” serta “Raja Ali Haji dan Orang Pesukuan dalam Kerajaan Riau Lingga”. Keduanya termuat dalam dua buku penting: Cakap-Cakap Rampai-Rampai dan Pada Masa Ini Sukar Dicari (Unri Press, 1998) dan Karena Emas di Bunga Lautan: Sekumpulan Esai-Esai Sejarah (Unri Press, 2002). Membaca ulang esai-esai ini hari ini terasa sangat menggugah, bahkan terasa seperti membaca refleksi atas realitas kekinian.
Seni Dapur Melayu: Gastronomi sebagai Identitas
Esai Seni Dapur dan Raja Ali Haji ditulis Hasan Junus tahun 1996, bertepatan dengan peringatan Hari Raja Ali Haji pada bulan Oktober. Tulisan ini telah berusia tiga dekade. Namun, jika dibaca hari ini, ia terasa sangat relevan bahkan terasa seolah ditulis untuk konteks masa kini.
Saat ini, kuliner telah menjelma menjadi gaya hidup. Acara televisi, kanal YouTube, media sosial, hingga rubrik-rubrik media cetak dipenuhi pembahasan tentang makanan. Kuliner tidak lagi sekadar urusan perut, tetapi menjadi simbol identitas, pariwisata, dan bahkan kebanggaan budaya. Namun, jauh sebelum istilah “wisata kuliner” populer, Hasan Junus sudah lebih dulu menulis tentang seni dapur Melayu sebagai penanda peradaban.
Bandingkan, misalnya, dengan Bondan Winarno, ikon kuliner Indonesia yang mulai dikenal luas sejak pertengahan tahun 2000-an melalui acara televisi dan kolom Jalan Sutra di harian Suara Pembaruan. Kolom itu kemudian berkembang menjadi komunitas kuliner nasional. Hasan Junus, melalui esainya tahun 1996, sudah lebih dulu meletakkan kuliner dalam bingkai kebudayaan dan sejarah.
Dalam esai tersebut, HJ membuka tulisannya dengan kalimat yang kuat dan menggugah:
“Ketinggian suatu budaya dapat ditandai dari banyaknya ragam dan rumitnya penghidangan seni dapur dalam kehidupan bangsa itu.”
Bagi HJ, negeri-negeri besar dan berbudaya tinggi selalu ditandai oleh seni dapur yang kaya, rumit, dan berjangkauan luas. Makanan, bersama musik, pakaian, dan kesenian lainnya, menjadi penanda identitas suatu puak. HJ bahkan menyentil cara pandang modernitas yang dangkal. Menjadi modern, tulisnya, bukan berarti berbusana Christian Dior, berkendara Renault, atau makan Kentucky Fried Chicken (KFC). Modern justru berarti mampu mengenakan busana setempat dan menghidangkan makanan khas daerahnya sendiri dengan bangga. Pernyataan ini terasa sangat relevan di tengah arus globalisasi yang kerap menyeragamkan selera dan gaya hidup.
Menariknya, Hasan Junus sudah menggunakan istilah gastronomi istilah yang kini sangat populer dalam kajian kuliner dan pariwisata. Mengutip Le Petit Larousse, gastronomi adalah pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan dapur: resep, seni mencicipi, dan menilai hidangan. Bagi HJ, gastronomi memiliki usia sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Dari teknik paling sederhana hingga paling kompleks membakar, menimbun, memanggang, merebus, menanak, hingga mengukus semua mencerminkan tahap-tahap peradaban.
Menurut HJ, seluruh tahapan gastronomi itu hadir dalam tradisi Melayu Riau dan Kepulauan Riau. Jejaknya dapat ditemukan dalam Kitab Pengetahuan Bahasa karya Raja Ali Haji. Dalam kamus tersebut tercatat beragam hasil seni dapur Melayu: otak-otak, apam, opor, epok-epok, engkak, bingka, emping, botok-botok, hingga acar. Bahkan, takrif makanan seperti otak-otak dijelaskan dengan rinci, menunjukkan betapa pentingnya dapur dalam kebudayaan Melayu.
HJ juga menyinggung surat Raja Ali Haji kepada H. von de Wall pada tahun 1868, yang menunjukkan upaya sistematis untuk mendokumentasikan penganan Melayu. Dalam naskah Kisah Pelayaran ke Riau, digambarkan jamuan tambul dan kue mue di rumah Tengku Embong Fatimah, lengkap dengan air kahwa, rendang pisang, dan sirup ros. Bahkan disebut pula adanya Raja Perak di Pulau Penyengat yang rajin mengumpulkan resep masakan hingga melahirkan manuskrip seni dapur Melayu. Semua ini menunjukkan bahwa kuliner Melayu bukan sekadar soal rasa, tetapi juga memori, identitas, dan peradaban.
Orang Pesukuan: Penghargaan yang Hilang
Esai kedua yang tak kalah relevan adalah “Raja Ali Haji dan Orang Pesukuan dalam Kerajaan Riau Lingga”, dimuat dalam buku Karena Emas di Bunga Lautan. Dalam esai ini, Hasan Junus mengulas kiprah Orang Pesukuan atau yang kerap disebut Orang Laut dalam sejarah Kerajaan Melayu Riau Lingga.
HJ mengurai berbagai literatur dengan bahasa yang mengalir. Salah satunya adalah karya Haji Ibrahim Orang Kaya Muda, Cakap-Cakap Rampai-Rampai Bahasa Melayu Johor (1868), yang menjelaskan pembagian kerja Orang Laut secara rinci: Orang Gelam sebagai pembuat perahu, Orang Ladi sebagai pendayung, Orang Kerayung sebagai pandai besi, dan seterusnya. Ini menunjukkan sistem sosial yang terorganisasi dan berbasis keahlian.
Hal yang paling menarik, HJ menunjukkan bahwa pada masa kesultanan, Orang Pesukuan tidak dipinggirkan. Mereka justru diberi penghargaan dan posisi terhormat. Pemimpin mereka bergelar batin, dengan struktur pemerintahan yang jelas—dibantu juru, jenang, dan akim serta berada di bawah koordinasi amir. Batin Cedun, misalnya, diberi gelar Datuk Nara Busana; Batin Singapura diberi gelar Datuk Raja Negara. Ini bukan gelar sembarangan, melainkan pengakuan atas jasa dan peran mereka dalam menjaga laut dan wilayah kerajaan.
Di bagian akhir, Hasan Junus menyentil pemerintah masa kini. Jika pemerintahan lama bahkan pada masa kolonial Belanda masih memberi perhatian pada Orang Laut, mengapa pemerintah sekarang justru tampak abai? Pertanyaan ini ditulis HJ puluhan tahun lalu, namun terasa semakin relevan hari ini. Orang Pesukuan masih kerap terpinggirkan, minim program pemberdayaan, dan hanya “diingat” menjelang momen politik.
Dua esai Hasan Junus ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasannya benar-benar melampaui zamannya. Ia membaca masa lalu untuk menafsir masa kini, dan menulis sejarah bukan untuk nostalgia, melainkan untuk refleksi. Di tengah derasnya arus globalisasi dan amnesia budaya, esai-esai HJ layak dibaca ulang—bukan hanya sebagai karya sastra sejarah, tetapi sebagai cermin untuk melihat siapa kita dan ke mana kita melangkah. Hasan Junus telah pergi, tetapi esai-esainya tetap hidup. Dan mungkin, di sanalah letak keabadiannya. **

