Konten dari Pengguna
Catatan Tentang Perang Tak Penting IPA dan IPS
24 Oktober 2025 11:39 WIB
·
waktu baca 5 menit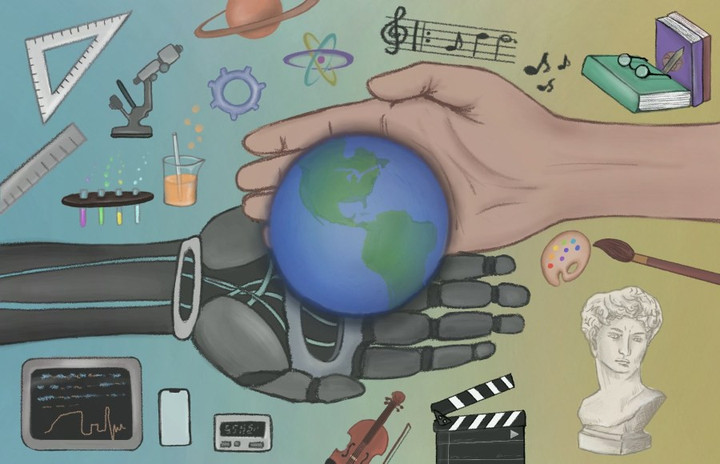
Kiriman Pengguna
Catatan Tentang Perang Tak Penting IPA dan IPS
Persoalan dunia nyata tidak datang sebagai kotak-kotak jurusan, tapi sebagai kompleksitas yang menuntut kolaborasi antara nalar matematis, kepekaan sosial, imajinasi artistik, dan keberanian politis.Dendy Raditya Atmosuwito
Tulisan dari Dendy Raditya Atmosuwito tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
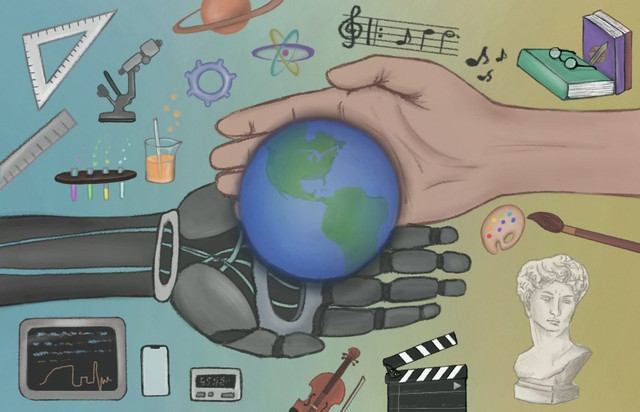
Ada sebuah kebiasaan ganjil yang tanpa sadar kita lestarikan dalam pergaulan sehari-hari: menjepit dan menjerat orang lain dengan label. Kita ciptakan kotak-kotak sempit, lalu kita paksakan orang lain masuk ke dalamnya. Kita menempelkan cap, seolah-olah hidup ini sesederhana memilih jurusan di SMA. Praktik ini punya nama keren: stigma. Istilah ini aslinya dari Yunani kuno, untuk menyebut tanda bakar pada kulit budak, kriminal, atau pemberontak. Sebuah penanda aib. Zaman sekarang, stigma tidak lagi dilukis dengan besi panas, ia diukir lewat kata-kata. Namun esensinya tak berubah, stigma selalu bermakna buruk.
Salah satu arena pertarungan stigma paling meriah di zaman kita, tentu saja, adalah palagan wacana antara kubu STEM (Sains, Teknologi, Teknik, Matematika) melawan kubu Sosial Humaniora. Anak IPA versus anak IPS. Sebuah perang abadi yang diwariskan dari bangku sekolah hingga ke ruang pembicaraan media sosi al, dari obrolan keluarga hingga ke debat kusir di media sosial. Kubu STEM dicitraikan sebagai kaum rasional, logis, dan pasti, namun dituduh kaku, apolitis, dan miskin kepekaan sosial. Sebaliknya, kubu Soshum dianggap kritis dan pandai bicara, namun dicap tak bisa lepas dari "katanya" dan alergi terhadap angka. Stigma-stigma ini begitu kuat, hingga kita lupa bertanya: benarkah demikian? Apakah kebenaran memang sesempit itu?
Sejarah, untungnya, punya selera humor yang bagus untuk menertawakan kekerdilan nalar kita. Mari kita mundur hampir seabad, ke tahun 1927. Di Brussels, Belgia, digelar sebuah konferensi akbar Liga Internasional Anti-Imperialisme. Panggung itu diisi oleh nama-nama besar: Mohammad Hatta dari Indonesia, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Ho Chi Minh dari Vietnam, dan para pejuang kemerdekaan lain dari seluruh dunia. Dalam sidang itu, mereka sepakat memilih seorang ilmuwan sebagai presiden kehormatan. Nalar stigmatik kita tentu akan menebak seorang ahli ilmu politik atau hukum internasional. Tapi tidak. Mereka justru memilih seorang fisikawan teoritis.
Nama fisikawan itu adalah Albert Einstein. Ya, Einstein yang itu. Bapak teori relativitas, yang foto ikoniknya menjulurkan lidah. Bagaimana bisa seorang ilmuwan eksak, yang seharusnya sibuk merenungkan lubang hitam di laboratoriumnya, justru didapuk memimpin sebuah gerakan politik global? Bukankah menurut kotak stigma kita, anak IPA itu seharusnya apolitis dan buta terhadap isu-isu sosial? Nyatanya, sejarah menampar logika sempit itu. Einstein adalah bukti bahwa kejeniusan tidak mengenal sekat jurusan.
Contoh lain yang lebih lampau dan tak kalah dahsyat adalah Leonardo da Vinci. Kita mengenalnya sebagai pelukis mahakarya Monalisa, seorang seniman humaniora tulen menurut kacamata kita. Namun, nalar stigmatik kita akan terdiam melihat buku catatannya yang dipenuhi sketsa detail tentang anatomi manusia, rancangan mesin terbang, dan konsep-konsep canggih di bidang teknik sipil. Da Vinci adalah seorang seniman sekaligus ilmuwan, seorang humanis sekaligus insinyur. Baginya, seni dan sains bukanlah dua dunia yang terpisah, melainkan dua cara berbeda untuk memahami keindahan dan misteri alam semesta.
Di era modern, lihat saja Yuval Noah Harari. Ia adalah seorang sejarawan, seorang anak IPS tulen. Tapi coba baca mahakaryanya, Sapiens. Untuk menjelaskan sejarah umat manusia, ia tidak hanya bicara tentang kerajaan dan perang. Ia justru memulai dari Revolusi Kognitif, meminjam gagasan dari biologi evolusioner dan ilmu saraf. Ia menjelaskan bagaimana gosip dan fiksi (ranah humaniora) menjadi alat bertahan hidup yang paling kuat bagi Homo sapiens (sebuah konsep biologi). Nalar stigmatik kita pasti korslet. Sejak kapan anak sejarah boleh bicara DNA dan evolusi? Harari merobohkan sekat itu, membuktikan bahwa untuk memahami humaniora, kita justru butuh sains.
Di sisi seberang, ada Carl Sagan. Ia adalah seorang astronom dan astrofisikawan kelas dunia. Dunianya adalah kosmos, galaksi, dan partikel debu bintang, ranah STEM paling puncak. Namun, warisan terbesarnya bagi peradaban bukanlah sekadar penemuan benda langit. Warisannya adalah kemampuannya untuk menerjemahkan keagungan kosmos menjadi narasi yang puitis dan filosofis melalui serial TV Cosmos. Ia tidak hanya bicara soal fisika, ia bicara soal tempat kita di alam semesta, tentang kerentanan kita sebagai "setitik debu pucat". Nalar stigmatik kita akan mencibir, "Ilmuwan kok puitis?" Sagan menunjukkan bahwa sains tanpa humaniora adalah data yang bisu, dan humaniora tanpa sains adalah cerita tanpa fondasi.
Kisah tentang gagalnya stigma menggambarkan realita pun berlanjut di halaman belakang kita, tepatnya di Yogyakarta. The Liang Gie adalah alumnus Fakultas Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM, seorang penulis yang sangat produktif. Di antara puluhan bukunya, ada satu judul yang membuat kening berkerut: 'Filsafat Matematika'. Nalar stigmatik kita pasti sulit menerima. Bagaimana bisa seorang alumnus FISIPOL, yang seharusnya alergi dengan angka dan statistika, justru mampu merenungkan hakikat filosofis dari matematika? Tapi bagi The Liang Gie, stigma itu hanya angin lalu.
Tokoh-tokoh dalam tulisan ini adalah monumen pengingat betapa tidak relevannya perdebatan antara STEM dan Sosial Humaniora. Pertarungan ini hanya mengokohkan stigma yang tidak ada manfaatnya, sebuah reduksi intelektual yang membuat kita gagal melihat potensi manusia secara utuh. Persoalannya bukan siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok-tembok imajiner ini. Karena pada akhirnya, tantangan dunia nyata tidak pernah datang dalam format soal pilihan ganda antar-jurusan. Ia datang sebagai masalah kompleks yang menuntut kolaborasi antara nalar matematis, kepekaan sosial, imajinasi artistik, dan keberanian politis.
Jadi, selamat tinggal stigma keilmuan. Perang tak penting ini sudah saatnya kita akhiri.

