Konten dari Pengguna
Tarutung: Ruang Antara dan Titik Tolak Intelektual Sitor Situmorang
9 Oktober 2025 17:39 WIB
·
waktu baca 8 menit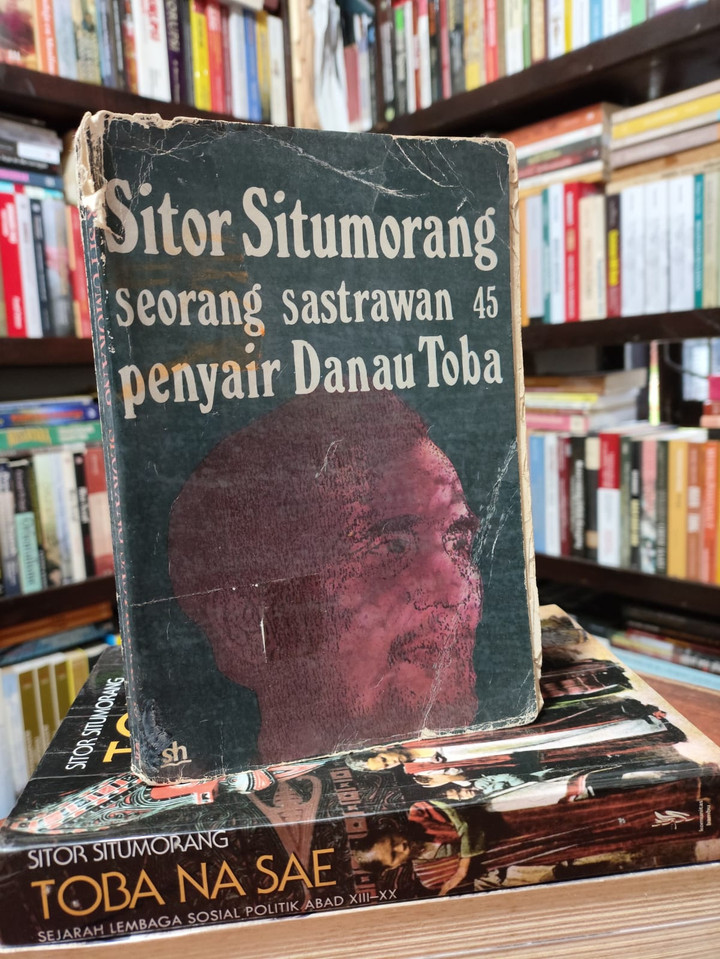
Kiriman Pengguna
Tarutung: Ruang Antara dan Titik Tolak Intelektual Sitor Situmorang
Tanpa Tarutung, Sitor Situmorang mungkin akan tetap terjebak dalam mitos di desanya, bukan menjadi seorang sastrawan yang menjelajahi zaman dan gagasan.Dian Purba
Tulisan dari Dian Purba tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
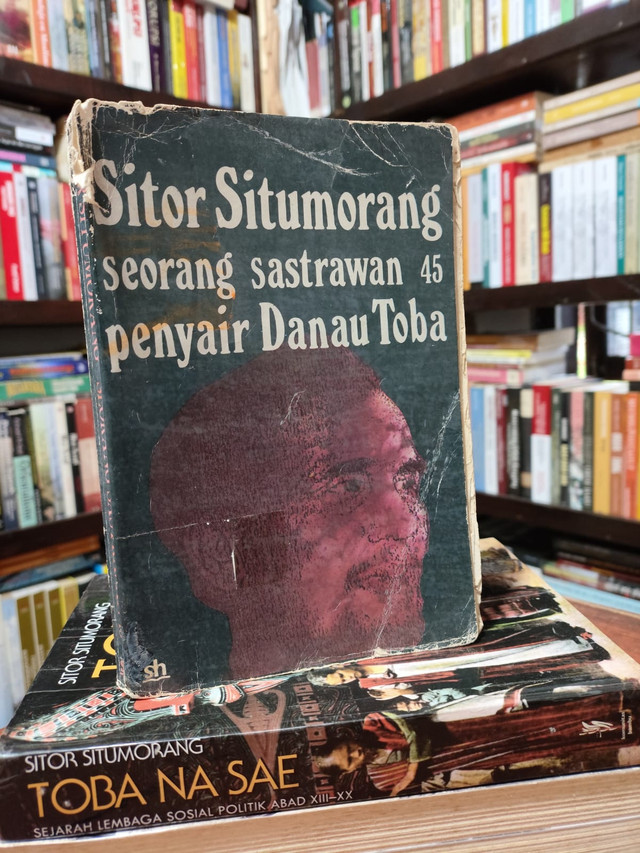
Sebagai kota yang menjadi “ruang antara” sekaligus “titik pental”, Tarutung memainkan peran penting dalam membentuk identitas intelektual Sitor Situmorang. Selama tiga tahun (1938–1941) di kota ini, Sitor tidak hanya mengalami transisi geografis dari desa asalnya, Harianboho, tetapi juga transisi mental yang signifikan, di mana ia mulai meninggalkan tradisi Bataknya yang lama dan merangkul dunia modern yang berfokus pada pendidikan dan karir. Proses ini tidaklah mulus; Sitor harus bergumul dengan ketegangan antara pendidikan kolonial Belanda yang ia dapatkan dan sikap paternalisme misionaris Kristen yang merendahkan kebudayaan Batak. Namun, dari pergulatan inilah lahir seorang individu yang tidak lagi terikat pada isolasi kesukuan, melainkan terobsesi pada dunia yang lebih luas, membawa visi kosmopolitan yang melampaui batas-batas Nusantara.
***
Sitor Situmorang lahir pada 2 Oktober 1924 di desa Harianboho, sebuah lembah kecil di kaki Gunung Pusuk Buhit. Tempat ini merupakan pusat dunia mitologis Batak yang kaya akan tradisi adat dan kepercayaan leluhur. Ayahnya adalah seorang kepala adat dan penganut kepercayaan asli Batak, meskipun ia sudah dibaptis sebagai Kristen pada tahun 1918. Ayah Sitor melihat Kekristenan dan pendidikan sebagai "zaman baru" yang berguna bagi anak-anaknya di masa depan, tanpa harus meninggalkan tradisi adatnya. Sitor pun tumbuh dalam situasi yang penuh pertentangan ini.
Perpisahan Sitor dari dunia asalnya dimulai saat usianya tujuh tahun. Ia dikirim ke Balige pada tahun 1931 untuk memulai Sekolah Dasar berbahasa Belanda, yang ia rasakan sebagai awal "berada di rantau". Balige, yang baginya adalah "kota pertama," merupakan kebalikan dari Harianboho. Kota ini menjadi pusat modernisasi, penyebaran agama Kristen, dan pendidikan berbahasa Belanda untuk anak-anak kepala adat.
Di Balige, Sitor melakukan penyesuaian yang sulit namun penting. Pada liburan pertamanya, ia melepaskan gelang perak di tangan dan kakinya yang merupakan simbol kebanggaan di desanya, karena ia ditertawakan oleh teman-teman di kota. Sitor menyebut tindakan ini sebagai "ras berkhianat mengalah kepada prasangka orang". Pelepasan gelang ini menandai kesediaannya untuk meninggalkan identitas visual tradisi lama demi beradaptasi. Peristiwa ini juga bersamaan dengan pengalaman pertamanya tentang modernitas, seperti menonton film koboi, minum es sirup, mendengar radio, dan melihat bengkel mobil. Di Balige, Sitor mulai menyadari bahwa dunia terbagi menjadi dua: dunia gaib dan dunia nyata yang terus berubah karena campur tangan manusia.
Transisi geografis dan mental Sitor berlanjut ke Sibolga dari tahun 1936 hingga 1938. Sebagai daerah pesisir yang terbuka dan kosmopolitan, Sibolga memperluas kesadaran Sitor dan menjauhkannya dari Harianboho. Namun, titik balik yang sesungguhnya terjadi saat ia pindah ke Tarutung.
Pangkalan Zaman Baru dan Inkubator Intelektual (1938–1941)
Sitor tiba di Tarutung pada usia 14 tahun pada tahun 1938 untuk masuk MULO (sekolah menengah pertama berbahasa Belanda). Jika Balige adalah pusat modernisasi, maka Tarutung adalah "pangkalan zaman baru untuk Tanah Batak". Kota ini adalah tempat misionaris Nommensen mendirikan gereja pertama, pusat pendidikan, dan basis awal kekuasaan Belanda.
Sitor mengakui tiga tahun di Tarutung (1938–1941) sebagai "masa terbahagia" dalam hidupnya, karena ia bebas dari tanggung jawab selain belajar. Pendidikan di MULO, dengan guru-guru Belanda dan mata pelajaran yang berfokus pada kehidupan Barat, secara tidak langsung menanamkan rasa superioritas pada siswa. Sitor menyatakan bahwa "perasaan jadi elite terpupuk di hati kira-kira 300 murid". Lingkungan MULO menyediakan standar hidup dan pendidikan yang sangat tinggi, yang mempersiapkan "segelintir generasi baru" untuk dunia modern. Walaupun dikelilingi oleh masyarakat Batak, pendidikan ini menjauhkan Sitor dari realitas rakyat. Ia diajari untuk mencintai Ratu Belanda dan lebih mengenal sejarah "tanah air Belanda" daripada sejarah tanah airnya sendiri.
Tarutung juga menjadi tempat penting bagi perkembangan intelektual Sitor. Ia melihat ilmu pengetahuan sebagai "siraman hujan yang dinanti-nantikan". Sitor memantapkan cita-cita karirnya untuk menjadi wartawan dan terjun ke dunia politik. Ia bahkan berambisi untuk masuk Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Ini menunjukkan bahwa Tarutung tidak hanya memberinya bahasa Belanda, tetapi juga ambisi untuk maju dan meraih "pangkat" tertinggi melalui pendidikan.
Dengan demikian, Tarutung menegaskan posisi Sitor sebagai "ruang antara sekaligus titik pental," di mana ia berada di tengah-tengah dua dunia: tradisi yang telah ia tinggalkan dan dunia modern yang ia cita-citakan. Tarutung menjadi tempat Sitor mematangkan dirinya untuk kehidupan yang sama sekali berbeda.
Pergulatan dengan Misi Kristen (Zending)
Pandangan Sitor terhadap Misi Kristen (Zending) di Tarutung sangat kompleks, mencerminkan ketegangan antara rasa hormat, penolakan, dan kesadaran akan proses sejarah.
Secara kultural, Sitor menolak sikap paternalisme misionaris. Ia melihat perbedaan antara pejabat kolonial Belanda dan misionaris. Misionaris asing "menganggap rendah kebudayaan Batak" yang terkait dengan kepercayaan lama. Mereka datang dengan "segala prasangka borjuis Eropa terhadap kebudayaan pribumi". Sitor mencatat bahwa misionaris sengaja menghindari penggunaan bahasa Belanda saat berbicara dengan siswa terdidik seperti dirinya, karena mereka menganggap bahasa tersebut "mengancam merusak".
Meskipun ada ketegangan rohani, Sitor dan keluarganya mengakui peran penting Misi. Ayahnya merasa "zaman baru telah datang," sehingga ia menyerahkan anak-anaknya kepada pendidikan gereja dan pemerintah. Sitor melihat bahwa gereja dan sekolah berfungsi sebagai "wadah sekularisme menuju nasionalisme". Bahkan, terpilihnya seorang pendeta Batak sebagai pemimpin gereja menggantikan pemimpin Jerman dianggap Sitor sebagai "nasionalisme Batak" yang terkait langsung dengan nasionalisme Indonesia. Sitor menyimpulkan bahwa Misi, dengan segala paternalismenya, secara ironis, telah membuka jalan bagi kesadaran nasional Indonesia.
Sitor memandang Misi dan gereja bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat sejarah yang membawa pendidikan dan modernitas. Hal ini memungkinkannya melepaskan diri dari isolasi kesukuan, sambil tetap mempertahankan kesetiaan mendalam kepada ayahnya dan tradisinya.
Tarutung sebagai Pembentuk Pribadi dan Intelektual
Tarutung menjadi tempat Sitor melepaskan identitas Batak lamanya (tradisi desa) dan mengenakan identitas Batak modern (elit terpelajar). Masa remajanya di Tarutung adalah "tahap pertarungan diam-diam antara penolakan dan taklid yang berlebihan". Namun, Sitor berhasil mengatasi konflik identitas ini dengan "memelihara loyalitas mendalam terhadap 'Ayah'". Ia meninggalkan bentuk-bentuk tradisi seperti gelang perak, tetapi tidak pernah meninggalkan inti tradisi yang diwakili oleh sosok ayahnya.
Direktur dan guru-guru sekolah Belanda meyakinkan Sitor bahwa ia "mampu mencapai apa saja". Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri yang menjadi modal utamanya. Di Tarutung, Sitor juga mematangkan benih kosmopolitan dan "romantisisme perjuangan" yang kelak menjadi ciri intelektualnya. Ia tertarik pada "karir" dan "politik," yang pada masa itu sering digabungkan dengan menjadi "sastrawan". Tarutung menjadi tempat Sitor bulat memutuskan untuk merantau ke Batavia (Jakarta) pada pertengahan 1941. Keputusan ini didukung penuh oleh keluarganya sebagai "proyek keluarga" untuk mencapai "pangkat" tertinggi.
Kelahiran Wartawan Revolusi (1943–1946)
Setelah rencana studinya gagal karena Perang Pasifik, Sitor kembali ke Tarutung pada tahun 1943. Kota ini telah menjadi pusat pemerintahan Jepang di pedalaman Tapanuli, memperkuat posisinya sebagai pusat dinamika politik. Di sinilah Sitor menyelesaikan pembentukan intelektualnya, yang mengubah ambisi remajanya menjadi aksi politik-jurnalistik.
Sitor diangkat sebagai pegawai di kantor gubernur Jepang, dengan tugas mengurus perpustakaan dan menerjemahkan kata-kata Belanda. Perpustakaan ini, yang berisi buku-buku Belanda yang disita, menjadi "laboratorium intelektual" bagi Sitor. Ia bahkan ditugaskan menerjemahkan kutipan dari Baron Tanaka yang menggarisbawahi filsafat imperialisme Jepang. Sitor, yang dibesarkan di bawah doktrin kemajuan Barat dan harga diri Batak, kini melihat wajah imperialisme Timur. Puncaknya, sekretaris Jepang secara rahasia menunjukkan pamflet Sekutu yang berisi berita kekalahan Jepang. Sitor menyadari goyahnya kekuasaan penjajah, yang memperkuat keyakinannya bahwa zaman pasti akan berubah.
Ketika Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945, Sitor menyadari bahwa kekuasaan kolonial, baik Barat maupun Timur, dapat runtuh dengan cepat. Tarutung menjadi tempat Sitor meninggalkan status pegawainya dan mengakhiri hubungan terakhirnya dengan penjajah, bersiap untuk memasuki era baru.
Segera setelah Jepang pergi, Sitor terlibat dalam pembentukan Komite Nasional Daerah (KND) Tapanuli. Di sinilah cita-cita karirnya menjadi kenyataan, dan Tarutung menjadi tempat kelahirannya sebagai wartawan. Sitor ditunjuk sebagai redaktur (editor) di koran kecil KND Tapanuli, Suara Nasional. Ini adalah langkah pertamanya di atas "tangga karir 'tulis-menulis'".
Bagi Sitor, menulis adalah aksi nyata. Ia merasa bahwa "tiap kata atau kalimat terasa langsung punya kaitan dengan pergolakan masyarakat". Ia memandang menulis sebagai "senjata mental yang dihujamkan ke arah musuh". Pengalaman ini menanamkan etos revolusioner dalam jurnalistiknya: menulis adalah perjuangan, dan kata-kata adalah senjata yang menggerakkan massa. Lingkungan KND Tapanuli, yang terdiri dari berbagai tokoh, memberi Sitor pemahaman tentang dinamika politik lokal dan nasionalisme Indonesia.
***
Tarutung bukanlah sekadar kota persinggahan bagi Sitor Situmorang, melainkan "jejak sejarah" yang membentuk identitasnya. Di Tarutung, Sitor menyelesaikan konflik internalnya dengan menanggalkan identitas Bataknya yang lama, tetapi mempertahankan inti kesetiaan dan harga dirinya. Pendidikan kolonial memberinya kerangka berpikir Barat, sementara ketegangan dengan Misi Kristen mematangkan kesadaran nasionalismenya.
Pergulatan ini melahirkan individu yang tidak lagi terikat oleh mitos kesukuan yang terisolasi, melainkan terobsesi pada dunia yang lebih luas dan perjuangan kebangsaan. Tarutung adalah tempat ia mengumpulkan "modal kultural" yang memungkinkannya menjadi seorang perantau sejati. Ia membawa cita-cita Tarutung untuk menyerap ilmu pengetahuan sebagai "siraman hujan" dan mengubahnya menjadi visi kosmopolitan yang melampaui batas-batas Nusantara. Tanpa Tarutung, Sitor Situmorang mungkin akan tetap terjebak dalam mitos di desanya, bukan menjadi seorang sastrawan yang menjelajahi zaman dan gagasan.

