Konten dari Pengguna
Jebakan Kuantitas dan Komersialisasi Jurnal di Perguruan Tinggi Indonesia
11 Oktober 2025 15:00 WIB
·
waktu baca 5 menit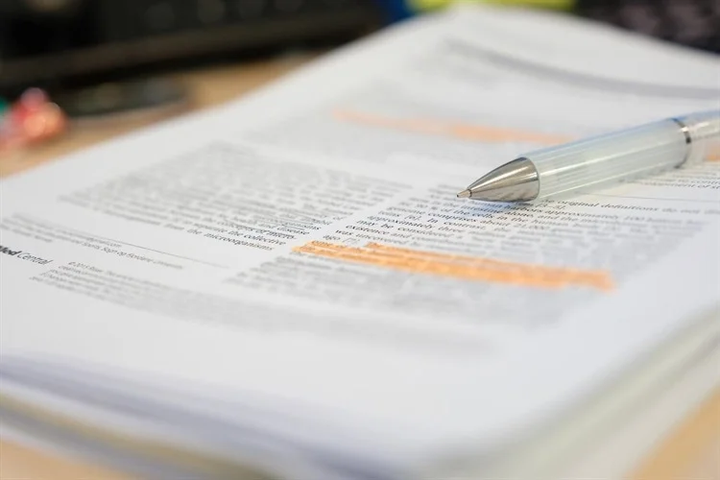
Kiriman Pengguna
Jebakan Kuantitas dan Komersialisasi Jurnal di Perguruan Tinggi Indonesia
Mengulas krisis integritas riset di perguruan tinggi Indonesia, dampak ekosistem publikasi predator, dan seruan untuk mereformasi sistem akademik agar kembali berlandaskan etika. #userstoryFikri Haekal Akbar
Tulisan dari Fikri Haekal Akbar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
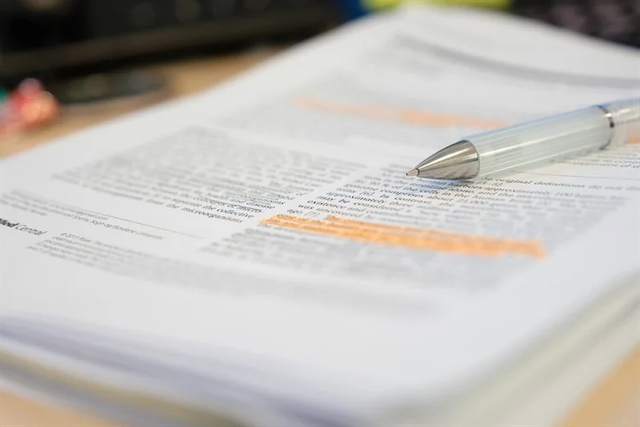
Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa 13 perguruan tinggi ternama di Indonesia masuk dalam daftar institusi dengan risiko integritas riset yang mengkhawatirkan menurut Research Integrity Index (RI²). Ironisnya, kabar ini tidak lagi mengejutkan. Peringkat “red flag” dan “high risk” tersebut bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan dari penyakit sistemik yang telah lama menggerogoti fondasi akademik kita yaitu obsesi buta terhadap kuantitas yang mengorbankan kualitas serta komersialisasi pendidikan yang perlahan mematikan nalar kritis dan etika keilmuan.
Fokus RI² pada R Rate (tingkat artikel yang ditarik) dan D Rate (persentase publikasi di jurnal yang dihentikan) secara telak menunjuk pada praktik-praktik tidak sehat yang dinormalisasi. Peringkat dan akreditasi—baik nasional (SINTA) maupun internasional (QS), yang terlalu mendewakan jumlah publikasi sebagai tolok ukur utama kehebatan institusi—telah mendorong para pengelola lembaga perguruan tinggi untuk menempuh jalan pintas. Tekanan semacam ini menimbulkan rantai masalah yang meluas, berawal dari rektorat ke fakultas, dari dekan ke dosen, hingga akhirnya beban terberat ditimpakan kepada mahasiswa, termasuk mahasiswa S1 yang seharusnya masih berada pada tahap fondasi pembelajaran riset.
Praktik yang mewajibkan mahasiswa S1 untuk mempublikasikan artikel di jurnal sebagai tugas mata kuliah atau syarat kelulusan adalah sebuah kekeliruan fatal yang berakar dari kebijakan yang salah arah. Pada tingkat sarjana, mahasiswa seharusnya difokuskan untuk memahami metodologi penelitian yang benar, pentingnya etika akademik, dan cara membangun argumen yang logis dan berbasis data.
Proses penulisan skripsi atau tugas akhir adalah latihan untuk itu semua. Namun, dengan memaksa mereka untuk "submit jurnal", tujuan pembelajaran tersebut bergeser menjadi sekadar pemenuhan syarat administratif. Akibatnya, yang kita saksikan adalah "banjir" artikel-artikel berkualitas rendah yang memadati repositori digital.
Penelitian yang dilakukan tergesa-gesa, analisis yang dangkal, kajian literatur yang minim, dan tak jarang, data yang kurang valid, semuanya demi mengejar tenggat waktu dan status "accepted". Pada akhirnya, jurnal-jurnal ini hanya menjadi tumpukan "sampah akademik" (academic junk) yang tidak memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tidak dapat direplikasi, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ironisnya, alih-alih meningkatkan sitasi dan reputasi, praktik ini justru menggerus kredibilitas institusi secara perlahan.
Di mana ada permintaan yang tinggi dan terdesak, di situ ladang bisnis baru akan muncul. Kondisi inilah yang melahirkan ekosistem jasa publikasi predator, sebuah pasar gelap akademik yang memangsa keputusasaan mahasiswa dan dosen yang dikejar target.
Ekosistem ini memiliki beberapa pemain utama. Pertama, adalah jurnal predator, yaitu penerbit yang beroperasi dengan kedok jurnal ilmiah, menjanjikan proses review dan publikasi sangat cepat dengan imbalan biaya. Mereka tidak memiliki proses telaah sejawat (peer review) yang kredibel dan menjadi penyumbang terbesar dari D Rate yang diukur oleh RI².
Kedua, adalah fenomena "joki jurnal" atau jasa publikasi "terima beres" yang menawarkan paket lengkap, mulai dari penulisan hingga jaminan terbit yang dinilai sebuah praktik penipuan intelektual. Ketiga, adalah para makelar jurnal yang bertindak sebagai perantara antara penulis dengan jaringan jurnal abal-abal, mengubah karya ilmiah menjadi komoditas dagang. Kehadiran ekosistem predator ini adalah racun yang paling mematikan karena tidak hanya menghasilkan riset berkualitas rendah, tetapi juga secara aktif menormalisasi kecurangan dan plagiarisme.
Kondisi ini menciptakan siklus yang terus memperkuat praktik-praktik keliru tersebut. Ketika proses penelaahan sejawat dapat dilewati dengan uang, kredibilitas seluruh isi artikel patut dipertanyakan. Ini adalah "praktik korupsi" dalam dunia akademik yang membiasakan generasi calon intelektual bahwa jalan pintas dan uang dapat membeli pengakuan akademis.
Bahayanya jelas, kita tidak lagi bisa memercayai data dan temuan yang dipublikasikan, meruntuhkan fondasi dasar dari penelitian ilmiah itu sendiri, yaitu kepercayaan (trust). Garis antara membayar Article Processing Charge (APC) yang sah di jurnal bereputasi dengan membayar "biaya siluman" ke jurnal predator menjadi kabur bagi mereka yang tidak teredukasi. Peringkat "red flag" dan "high risk" dari RI² adalah cermin dari akumulasi praktik-praktik buruk ini. Dunia internasional melihat data dan data menunjukkan bahwa banyak publikasi dari Indonesia bermasalah. Ini bukan lagi sekadar masalah internal, melainkan rusaknya reputasi akademik bangsa di kancah global.
Dampak destruktif ini bukanlah lagi sekadar hipotesis atau kekhawatiran karena ia sudah terjadi dan memakan korban. Belum lama ini, kita dikejutkan dengan berita tentang salah satu perguruan tinggi negeri ternama yang terpaksa mencabut gelar guru besar seorang akademisinya. Apa penyebab utamanya? Sejumlah karya ilmiah yang menjadi syarat utama pencapaian gelar akademik tertinggi tersebut terbukti diterbitkan di jurnal-jurnal yang teridentifikasi sebagai predator.
Kasus ini adalah bukti nyata dan paling gamblang bahwa jalan pintas melalui publikasi nirintegritas tidak hanya merusak reputasi institusi, tetapi juga dapat menghancurkan karier seorang akademisi. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap sistem yang rapuh pada akhirnya akan runtuh oleh kerusakan yang diciptakannya sendiri.
Maka dari itu, perlu ada perombakan total dan bukan lagi waktunya untuk penyangkalan atau mencari kambing hitam. Bagi regulator seperti Kemendikbudristek dan BRIN, evaluasi ulang secara radikal indikator kinerja berbasis kuantitas dan buatlah metrik yang menghargai kualitas, dampak, serta orisinalitas. Terbitkan daftar hitam (blacklist) resmi untuk jurnal dan jasa publikasi predator.
Bagi pimpinan perguruan tinggi, hentikan kebijakan yang memaksa publikasi dan bangunlah budaya integritas dari atas dengan mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan etika riset. Sementara itu, para dosen dan peneliti harus menjadi garda terdepan integritas dengan membimbing mahasiswa secara benar dan menolak segala jalan pintas.
Laporan RI² mesti dibaca sebagai alarm peringatan yang menggugah nurani akademik kita. Selama tidak ada reformasi mendasar, kita hanya akan sibuk menumpuk publikasi demi statistik; tanpa nilai, tanpa dampak, dan tanpa integritas.

