Konten dari Pengguna
Hilirisasi, Investasi, dan Perubahan Arah Rasionalitas Kebijakan Publik Nasional
15 Januari 2026 16:41 WIB
·
waktu baca 8 menit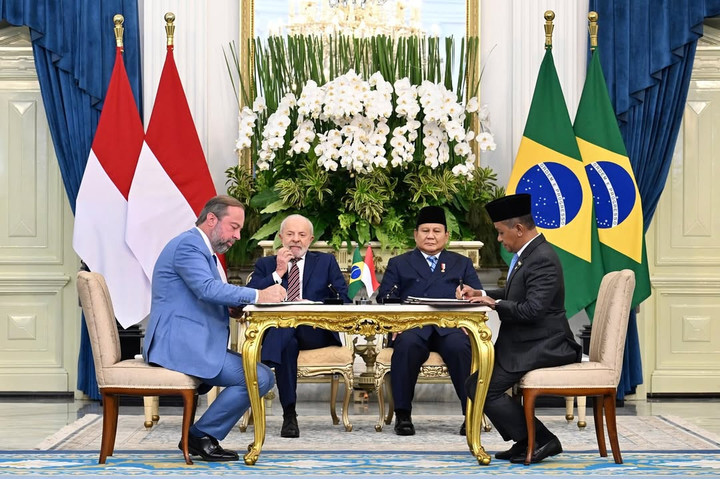
Kiriman Pengguna
Hilirisasi, Investasi, dan Perubahan Arah Rasionalitas Kebijakan Publik Nasional
Demokrasi yang pada akhirnya, bukan sebatas museum prosedur yang dipuja, melainkan bengkel sosial yang harus terus diperbaiki agar tetap relevan dengan tantangan zaman.Luthfi Ridzki Fakhrian
Tulisan dari Luthfi Ridzki Fakhrian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
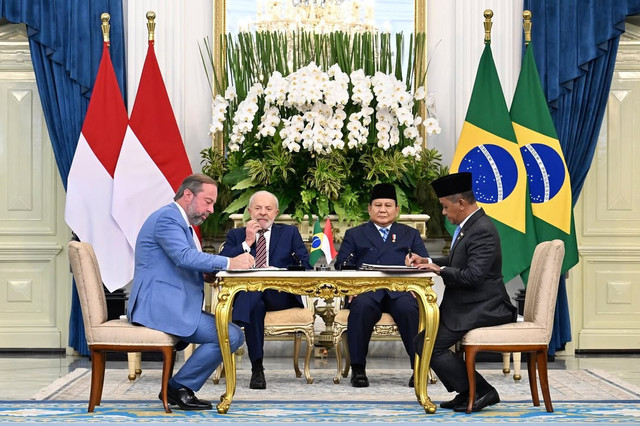
Demokrasi tidak pernah benar-benar hidup di ruang hampa. Ia selalu bekerja dalam struktur sosial, ekonomi, dan kekuasaan tertentu, sering kali jauh dari ideal normatif yang kita bayangkan. Ketika Bahlil Lahadalia melontarkan gagasan koalisi permanen dan membuka kembali diskursus Pilkada melalui DPRD, respons publik cenderung refleks dalam kecurigaan, resistensi, bahkan tudingan kemunduran demokrasi. Namun politik, sebagaimana diingatkan Pierre Bourdieu dalam The Logic of Practice (1990), tidak bisa dibaca hanya dari permukaannya. Praktik politik selalu dibentuk oleh struktur objektif yang bekerja secara laten melalui distribusi modal, kepentingan, dan relasi kekuasaan.
Bahlil bukanlah politisi yang lahir dan tumbuh dari ruang steril elite besae. Latar belakang dan rekam jejaknya sebagai pengusaha daerah, birokrat, hingga akhirnya memimpin partai besar telah membentuk satu habitus politik yang sangat khas, pragmatis, berorientasi hasil, dan sensitif terhadap biaya sosial dari sebuah sistem. Dalam kerangka Max Weber yang tertulis di Politics as a Vocation (1919), dijelaskan bahwa ini ialah tipe kepemimpinan dengan ethic of responsibility, yakni kepemimpinan yang berani menimbang konsekuensi nyata kebijakan, bukan sekadar atau berdasar pada kepuasan moral atau simbolik.
Pilkada Langsung dan Kelelahan Demokrasi Elektoral
Pilkada langsung adalah salah satu capaian penting dalam Reformasi 1998. Namun selama dua dekade berjalan, tanda-tanda kelelahan demokrasi elektoral menjadi semakin nyata. Data Kementerian Dalam Negeri setidaknya menunjukkan bahwa total biaya yang harus keluar dalam Pilkada Serentak 2024–2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp70 triliun, terdiri dari dana APBD daerah dan hibah APBN melalui KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. Angka ini belum termasuk biaya tidak langsung yang ditanggung kandidat dan partai politik.
Di sisi lain, KPU juga mencatat rata-rata biaya kampanye kepala daerah di provinsi besar bisa mencapai sekitar Rp100–300 miliar per kandidat, sementara di tingkat kabupaten/kota berkisar Rp20–50 miliar. Biaya tinggi ini menciptakan insentif kuat bagi politik uang dan praktik rente pasca-terpilih. Joseph Schumpeter dalam Capitalism, Socialism and Democracy (1942), telah sejak lama mengingatkan bahwa demokrasi yang terlalu mahal akan sangat berisiko berubah menjadi mekanisme seleksi elite berbasis modal, bukan lagi bersandar pada kompetensi.
Dalam konteks inilah wacana Pilkada melalui DPRD perlu dibaca ulang dan dikaji secara cermat. Robert Dahl dalam Polyarchy (1971), menyebut demokrasi modern sebagai polyarchy, di mana kualitas representasi dan akuntabilitas institusi sama pentingnya dengan partisipasi langsung. Soedjatmoko bahkan dalam Dimensi Manusia dalam Pembangunan (1985), juga menegaskan bahwa demokrasi di negara berkembang harus mempertimbangkan kapasitas institusional dan beban sosialnya, bukan sekadar meniru bentuk formal negara maju.
Bahlil secara dalam dan tegas telah membaca realitas nyata ini sebagai sebuah persoalan yang sangat struktural, bukan ideologis. Ia melihat kepala daerah hasil Pilkada langsung sering kali lahir dengan beban politik yang besar, namun tanpa dukungan legislatif yang solid, sehingga menjadi semacam anomali dari sebuah kombinasi yang justru melemahkan efektivitas pemerintahan daerah.
APBN, Efisiensi Politik, dan Rasionalitas Negara
Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, pertanyaan soal efisiensi demokrasi hari ini menjadi sangat relevan. APBN 2024 setidaknya telah mencatat bahwa belanja negara mencapai lebih dari Rp3.300 triliun, dengan tekanan besar pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Setiap rupiah yang telah dikeluarkan negara idealnya memiliki opportunity cost yang jelas.
Bahlil dalam hal ini setidaknya telah berhasil menempatkan demokrasi dalam sebuah logika manajerial negara, tentang bagaimana mekanisme politik tidak justru menggerus kapasitas fiskal untuk pelayanan publik. Hal ini selaras dengan pandangan Douglass North dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990), yang bahkan juga menegaskan bahwa institusi politik yang buruk bukan hanya persoalan dan masalah normatif, tetapi juga sumber inefisiensi ekonomi jangka panjang.
Di titik ini, langkah dan kritik terhadap Pilkada langsung bukan berarti menolak sebuah demokrasi, melainkan sebuah upaya untuk mengoreksi desainnya. Nurcholish Madjid dalam Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (1987), juga pernah mengingatkan bahwa demokrasi sejati tidak diukur dari banyaknya ritual prosedural, tetapi dari kemampuannya dalam menghadirkan keadilan dan kemaslahatan publik. Jika mekanisme yang ada justru malah memperbesar biaya dan mempersempit kualitas kepemimpinan, maka melakukan sebuah evaluasi adalah keniscayaan etis.
Koalisi Permanen dan Stabilitas Pemerintahan
Gagasan koalisi permanen yang diusung oleh Bahlil juga lahir dari proses dewasa dan pembacaan realistis atas sistem presidensial multipartai di Indonesia. Data DPR menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, hampir seluruh pemerintahan menghadapi fragmentasi dukungan politik yang sangat tinggi, sehingga memaksa presiden melakukan kompromi kebijakan yang tidak selalu optimal.
Giovanni Sartori dalam Parties and Party Systems (1976), menyebut kondisi ini sebagai sebuah polarized pluralism, di mana banyaknya partai tanpa ikatan koalisi jangka panjang justru melemahkan kapasitas pengambilan keputusan. Arend Lijphart dalam Patterns of Democracy (1999), juga menambahkan bahwa demokrasi dalam bentuk konsensus dan dengan koalisi stabil, justru sebenarnya lebih cocok bagi masyarakat yang majemuk, karena dapat menekan konflik elite yang destruktif.
Koalisi permanen bukan berarti hadir dengan meniadakan oposisi, melainkan sebuah upaya menciptakan garis kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Dalam tradisi Golkar sebagai catch-all party, pendekatan ini selaras dan sejalan dengan prinsip “The Golkar Way”, yakni politik dengan jalan tengah, moderat, dan berorientasi pads stabilitas. Otto Kirchheimer (1966), menyebut tipe partai ini sebagai bentuk adaptasi rasional terhadap kompleksitas masyarakat modern.
Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (1977), juga pernah mengkritik budaya politik Indonesia yang sangat gemar memuja dan memuji simbol demokrasi, tetapi terlihat sangat enggan dan acuh tak acuh dalam membangun konsep disiplin politik. Koalisi permanen sebenarnya jika dijalankan secara transparan, justru dapat sangat bisa menjadi sebuah bentuk disiplin politik tersebut.
Bahlil Lahadalia dan Keberanian Menyentuh Struktur
Langkah seorang Bahlil menjadi sangat menarik bukan karena ia tanpa risiko, melainkan karena ia tampil dengan secara sadar dan penuh telah menyentuh wilayah yang selama ini sering dihindari oleh banyak elite politik, yakni struktur biaya dan insentif demokrasi. Di titik ini, Bahlil tidak sedang hanya sedang bermain di level permukaan, seperti retorika prosedural atau simbol partisipasi, melainkan telah masuk ke bagian dari lapisan terdalam sebuah demokrasi, dengan bagaimana sistem membentuk sebuah perilaku, pilihan, dan bahkan moral para aktornya. Ia tidak hanya berbicara dari menara gading yang sangat normatif, tetapi juga hadir dari pengalaman langsung mengelola negara, partai, dan konflik kepentingan yang nyata.
Pendekatan ini juga selaras dengan gagasan rekayasa sosial (social engineering) sebagaimana dipahami oleh Jalaluddin Rakhmat. Dalam tulisannya, Rekayasa Sosial (1999), Jalaluddin Rakhmat menekankan bahwa perubahan sosial yang efektif tidaklah cukup mengandalkan seruan moral atau kesadaran individual, melainkan harus menyentuh bagian dari desain sistem, struktur insentif, dan arsitektur komunikasi kekuasaan. Dalam konteks ini, wacana akan Pilkada DPRD dan koalisi permanen dapat dibaca sebagai upaya mengubah bentuk perilaku politik dengan mengubah strukturnya, bukan sekadar menasihati aktor agar lebih bermoral.
Bahlil tampaknya telah memahami satu hal dasar yang sangat penting, bahwa demokrasi yang mahal akan selalu menghasilkan politik yang transaksional, betapapun idealnya niat para pelakunya. Maka, alih-alih terus menuntut aktor politik agar tampil “bersih” dalam sistem yang mahal dan kompetitif, ia justru mengajukan sebuah argumen dengan pertanyaan yang lebih radikal dan terukur, yakni apakah sistemnya sendiri perlu direkayasa ulang. Inilah inti rekayasa sosial, bukan dengan memaksa manusia menjadi malaikat, tetapi mendesain institusi agar manusia tidak hanya terdorong menjadi predator politik.
Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958), menulis bahwa politik hanya dapat benar-benar hidup ketika aktor berani tampil di ruang publik dengan gagasan yang tidak selalu nyaman, bahkan berisiko disalahpahami. Dalam konteks demokrasi di Indonesia yang kian hari semakin riuh, mahal, dan penuh sinisme, keberanian Bahlil dan Partai Golkar dalam membuka diskursus tentang biaya politik dan efektivitas institusi justru menjadi satu simbol dan tanda dari kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara, dan bukan pengkhianatan terhadap demokrasi.
Keberanian ini juga menandai sebuah pergeseran penting, dari demokrasi sebagai ritual prosedural menuju demokrasi sebagai alat pengelolaan konflik dan pembangunan. Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), telah mengingatkan bahwa dalam masyarakat yang sedang berubah cepat, stabilitas politik sering kali tidak lahir dari proses perluasan partisipasi tanpa batas, melainkan hadir dari inovasi institusional yang mampu menyalurkan partisipasi secara tertib. Demokrasi yang tidak ditopang oleh institusi yang adaptif justru berisiko melahirkan instabilitas kronis.
Dalam kerangka Jalaluddin Rakhmat, apa yang dilakukan oleh Bahlil dan Partai Golkar dapat dipahami sebagai rekayasa kesadaran politik kolektif. Ia memaksa publik dan elite keluar dari zona nyaman dari narasi moralistik menuju diskursus struktural, tentang siapa diuntungkan oleh sistem yang mahal, siapa tersisih, dan bagaimana negara seharusnya mengintervensi desain demokrasi agar lebih adil dan efektif. Rekayasa sosial, dalam arti ini, bukan manipulasi, melainkan intervensi sadar untuk kebaikan bersama.
Pada akhirnya, gagasan koalisi permanen dan Pilkada DPRD memang tidak boleh diterima secara dogmatis. Ia harus hadir dengan diuji secara rasional, berbasis data, dan melalui deliberasi publik yang jujur dan transparan. Namun menolaknya sejak awal tanpa membaca problem struktural yang hendak disentuh justru sangat amat berisiko mempertahankan status quo yang mahal dan melelahkan.
Rasionalitas Bahlil Lahadalia dan Partai Golkar, meski dengan segala kontroversinya, dapat dibaca sebagai upaya menertibkan demokrasi yang kian hari terlalu riuh, bukan dengan membungkam suara rakyat, tetapi dengan merekayasa ulang struktur demokrasi agar suara itu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang bekerja. Demokrasi yang pada akhirnya, bukan sebatas museum prosedur yang dipuja, melainkan bengkel sosial yang harus terus diperbaiki agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

