Konten dari Pengguna
Ketika Wacana Menjadi Virus
24 November 2025 7:00 WIB
·
waktu baca 8 menit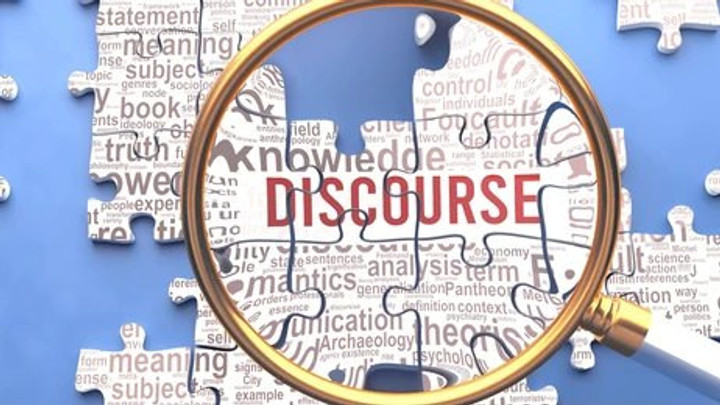
Kiriman Pengguna
Ketika Wacana Menjadi Virus
Ketika wacana menjadi virus, antibodi kognitiflah yang menjaga agar kita tidak ikut terinfeksi oleh ketergesa-gesaan. Akhirnya, yang viral mungkin video dan yang harus tetap waras adalah diri sendiri.Sawqi Saad El Hasan
Tulisan dari Sawqi Saad El Hasan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Beberapa minggu lalu, ruang digital Indonesia kembali diguncang oleh beredarnya sebuah video lama yang menampilkan interaksi seseorang dengan sekelompok anak. Walaupun potongan itu tidak memuat konteks lengkap, fragmen visual tersebut cukup memantik reaksi emosional yang meluas. Dalam hitungan jam, diskusi kecil menjelma menjadi arus perdebatan yang massif. Sebuah pola yang terasa semakin akrab dalam lanskap komunikasi kita.
Fenomena ini memperlihatkan hal penting: publik bukan hanya bereaksi terhadap konten, tetapi terhadap bagaimana konten itu mengaktifkan mekanisme psikologis dan sosial yang telah lama tertanam dalam masyarakat. Fragmen digital bekerja seperti virus; bukan karena fragmen digital berbahaya pada dirinya sendiri, tetapi karena fragmen digital menemukan inang yang tepat, yaitu emosi publik, nilai sosial yang sensitif, serta algoritma media sosial untuk berkembang biak.
Arus Bawah Psikologis
Apabila kita melihat fenomena tersebut dalam ilmu kognitif, kesan pertama hampir tak pernah netral. Kahneman (2011) menjelaskan bahwa ketika manusia berhadapan dengan stimulus mengejutkan, terutama yang menyangkut kelompok rentan seperti anak, otak mengaktifkan mekanisme penilaian cepat yang lebih dekat pada insting ketimbang analisis. Mekanisme ini adaptif dalam konteks evolusi, tetapi kurang selaras dengan ritme informasi digital yang terpotong dan serba cepat.
Video pendek itu pada dasarnya hanyalah pemicu. Respons besar lahir dari cara otak memproses fragmen: bukan dengan analisis mendalam, tetapi melalui intuisi moral. Nickerson (1998) menyebutnya bias konfirmasi, kecenderungan memperkuat impresi awal. Publik merasa telah memahami keseluruhan konteks dari potongan sempit, padahal pemahaman itu dibangun oleh intuisi, bukan kelengkapan informasi.
Perilaku tersebut selaras dengan riset perilaku konsumen. Bettman et al. (1998) serta Payne et al. (1993) menunjukkan bahwa manusia sering memilih jalur pintas (low-effort processing) saat menghadapi informasi kompleks. Dalam konteks video viral, warganet bertindak sebagai konsumen informasi: memilih interpretasi yang paling mudah dan paling selaras dengan emosi dominan.
Ketika komentar awal bernada marah, publik menafsirkannya sebagai norma moral kolektif. Inilah mekanisme pembuktian sosial (social proof) yang dijelaskan Cialdini (2007). Kita tidak hanya melihat konten, tetapi juga bagaimana orang lain melihatnya. Emosi pun bergerak seperti gelombang.
Tambahan data memperkuat gambaran ini: Survei Mastel (2023) mencatat bahwa 68% warganet Indonesia mengaku pernah menyebarkan konten viral tanpa memverifikasi kebenaran, sementara riset APJII 2024 menunjukkan 45% responden merasa “terbawa emosi” ketika melihat konten menyangkut isu moral.
Fenomena ini juga memunculkan heuristik representasi yang merupakan kecenderungan menyamaratakan satu potongan perilaku sebagai gambaran seluruh kelompok sosial. Oleh sebab itu, publik bukan lagi menilai video itu, melainkan menilai kelompok yang mereka bayangkan ada di balik video tersebut. Semua lapisan ini diperkuat oleh apa yang disebut Sloman & Fernbach (2017) sebagai illusion of explanatory depth: keyakinan bahwa kita memahami sesuatu secara utuh, padahal yang kita pahami hanyalah permukaannya.
Bayangan Algoritmik
Di atas arus psikologis itu, ada lapisan lain yang memperkuat gejolak, yaitu algoritma. Penelitian Vosoughi, Roy dan Aral (2018) menunjukkan bahwa informasi yang memicu kemarahan moral menyebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi netral. Algoritma media sosial tidak memiliki nurani; algoritma hanya membaca pola keterlibatan: seberapa cepat respons muncul, seberapa intens emosinya dan seberapa sering interaksi berulang.
Ketika fragmen visual menyangkut anak pada kategori high-valence emotion yang menunjukkan indeks emosi naik tajam. Algoritma menangkap sinyal itu dan memperluas distribusinya. Publik juga merasa seolah isu itu berada “di mana-mana”, meski itu hanya amplifikasi digital.
Perkara yang sering terlupakan adalah bahwa algoritma tidak netral. Algoritma dirancang oleh manusia, sering kali para insinyur dari Silicon Valley, membawa nilai dan budaya yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Sistem deteksi harmful content di negara yang lebih sekuler kadang tidak memahami nuansa hubungan antara figur agama, otoritas moral dan sensitivitas masyarakat Nusantara. Ketika standar itu diterapkan di sini, respons publik dan mekanisme platform kerap berjalan tidak seirama.
Oleh sebab itu, penting menegaskan bahwa teknologi bukanlah dalang tunggal. Algoritma memengaruhi kita, tetapi cara kita merespons algoritma sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, norma sosial, serta narasi yang sudah kita warisi sejak lama. Di negara dengan sensitivitas moral tinggi seperti Indonesia, satu potongan video dapat memicu reaksi sosial yang berbeda dibandingkan negara yang lebih sekuler. Dengan kata lain, teknologi adalah panggungnya, tetapi manusialah yang membawa naskah, aktor, dan tafsirannya masing-masing.
Di atas hal tersebut, ada yang bisa disebut algoritma wacana: aturan tidak tertulis tentang siapa yang layak dicurigai, siapa yang layak dibela, dan bagaimana isu dimaknai. Foucault (1972) menyebut wacana sebagai struktur yang membentuk subjek, bukan sekadar wadah. Dalam isu anak, wacana perlindungan moral menjadi gravitasi yang menarik semua argumen ke titik urgensi yang sama. Ketika algoritma platform bertemu algoritma wacana, ruang digital berubah menjadi akselerator makna. Emosi publik bukan hanya menyebar, tetapi diperbesar dan dipercepat secara sistemik.
Di balik semua itu, ada dimensi lain yang sering luput dari percakapan publik: viralitas adalah bisnis. Setiap lonjakan kemarahan, setiap ribuan komentar yang muncul dalam satu malam, adalah sinyal ekonomi bagi platform. Dalam istilah ekonomi perhatian, emosi adalah mata uang, dan keterlibatan, walaupun dipicu oleh keresahan adalah komoditas yang diperdagangkan.
Viralitas bukan sekadar fenomena sosial karena viralitas merupakan peristiwa komersial. Oleh karena itu, tak mengherankan bila konten yang paling memicu emosi justru paling cepat didorong oleh mesin platform. Algoritma tidak hanya menata alur informasi, tetapi juga mengelola arus nilai ekonomi yang bergantung pada keberlanjutan keterlibatan.
Pertarungan Makna yang Sunyi
Isu viral sering tampak seperti polarisasi, padahal isu viral lebih tepat dipahami sebagai keberagaman epistemi. Sebuah cara yang berbeda orang memaknai informasi. Sebagian melihat sebagai ancaman moral, sedangkan sebagian orang menekankan konteks sosial, sebagian melihatnya sebagai refleksi kerentanan publik, sementara sebagian lainnya telah membacanya sebagai simbol representasi figur atau kelompok tertentu.
Respons publik tidak muncul dari ruang kosong. Respons publik yang muncul dipandu pengalaman hidup, preferensi moral, serta struktur kognitif masing-masing. Di Indonesia, nilai religiusitas terikat erat dengan struktur sosial. Sebuah isu moral hampir selalu didekati dengan bingkai spiritual. Pada satu sisi ini menunjukkan kepedulian; sedangkan pada sisi yang lain, nilai keagamaan yang luhur kadang ikut terseret dalam perebutan makna di ruang digital.
Dalam kondisi seperti ini, setiap kelompok menciptakan realitasnya sendiri. Realitas itu koheren di dalamnya, tetapi sering bertentangan satu sama lain. Perdebatanpun mulai bergeser: bukan lagi tentang apa yang ada di dalam video itu, tetapi tentang seperti apa masyarakat ingin dipahami. Penting menekankan bahwa pola-pola ini bukan ciri kelompok tertentu, melainkan pola manusiawi yang muncul dalam situasi informasi yang serba cepat.
Data yang dihimpun oleh beberapa studi lokal mengenai dinamika framing di media sosial menunjukkan bahwa kecenderungan untuk membela “ingroup” dan mengkritik “outgroup” muncul lintas spektrum, lintas komunitas, dan lintas preferensi ideologis. Artinya, yang kita hadapi bukanlah masalah identitas politik tertentu, tetapi pola universal tentang bagaimana manusia mencari kepastian di tengah banjir informasi.
Di Antara Reaksi dan Refleksi
Kekacauan informasi ini menunjukkan bahwa ruang digital bekerja dalam dua ritme: ritme cepat emosi dan ritme lambat refleksi. Tantangan kita adalah menjaga keduanya tetap seimbang. Solusinya bukan memusuhi teknologi, tetapi menyusun ulang cara kita berinteraksi dengannya. Penelitian Rand dkk. (2019) menunjukkan bahwa jeda sesingkat satu detik bisa menurunkan kecenderungan untuk menyebarkan informasi keliru. Lima detik memberi ruang lebih besar bagi otak untuk berpindah dari impuls ke evaluasi.
Di sinilah pentingnya membangun antibodi kognitif yang menjadi kebiasaan kecil yang memperkuat ketahanan pikiran. Cara kerjanya sederhana, sering kali bahkan terasa seperti cerita kecil di kepala sendiri. Bayangkan saat ini kita sedang melihat sebuah video yang membuat dada terasa hangat atau geram. Sebelum jari bergerak mengetik komentar, ada baiknya memberi satu jeda pendek dengan seolah berkata pada diri sendiri: “Sebentar… apa sebenarnya yang kulihat?”
Pertanyaan reflektif kemudian muncul perlahan, satu per satu, seperti obrolan lembut dengan diri sendiri: :Apakah aku benar-benar melihat konteks yang utuh, atau hanya fragmennya saja?: Lalu muncul pertanyaan kedua, yang lebih jujur: ”Reaksiku ini datang dari bukti, atau hanya dari getaran emosiku yang pertama?” Akhirnya, pertanyaan yang membuka jendela ke arah yang lebih luas: ”Jika emosiku naik secepat ini… siapa yang sebenarnya diuntungkan?”
Pertanyaan-pertanyaan kecil ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan empati. Justru sebaliknya bertujuan menjaga empati agar tidak dibajak oleh amplifikasi emosional. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu telah memberi ruang bagi hati untuk tetap hangat, tanpa membuat kepala kehilangan kejernihannya. Menyadari bahwa platform digital dirancang untuk mempercepat keterlibatan, bukan memperdalam pemahaman, juga membantu kita berhenti menganggap bahwa apa yang “ramai” adalah apa yang “penting”.
Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah yang membentuk kekebalan pikiran. Seperti atlet yang melatih refleks, masyarakatpun dapat melatih refleks kognitifnya: bukan menahan kepedulian, tetapi memastikan kepedulian tidak diarahkan oleh kepanikan atau manipulasi.
Kontroversi digital tidak akan hilang, sedangkan algoritma tidak akan melambat. Namun kedewasaan kolektif tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita marah, melainkan seberapa panjang kita memberi ruang bagi nalar sebelum marah. Di ruang sempit antara melihat dan menghakimi antara reaksi pertama dan refleksi setelahnya, terdapat kesempatan untuk menjaga kewaspadaan moral tanpa mengorbankan kejernihan sosial.
Namun tentu saja, ketahanan berpikir individual bukanlah jawaban tunggal. Kita membutuhkan upaya yang bergerak dari dua arah: dari individu yang memperlambat reaksi, serta dari struktur yang memperlambat penyebaran misinformasi. Di negara-negara Nordik, misalnya, literasi digital diperkuat dengan regulasi transparansi algoritmik dan kewajiban platform untuk mengurangi amplifikasi konten bernada ekstrem. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa ketenangan publik tidak hanya bergantung pada kedewasaan warganya, tetapi juga pada keberanian platform dan pemerintah untuk merapikan arsitektur ruang digital.
Ketika wacana menjadi virus, antibodi kognitiflah yang menjaga agar kita tidak ikut terinfeksi oleh ketergesa-gesaan. Pada akhirnya yang viral mungkin video, tetapi yang harus tetap waras adalah diri kita sendiri.

