Konten dari Pengguna
Blind Box dan Budaya Konsumerisme Baru
5 Juni 2025 19:25 WIB
·
waktu baca 5 menit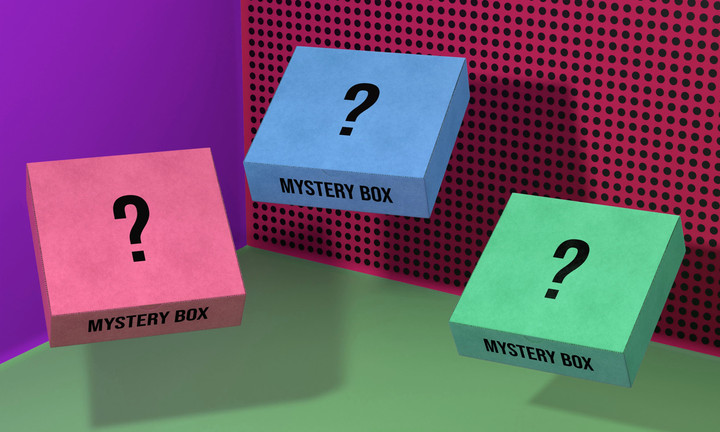
Kiriman Pengguna
Blind Box dan Budaya Konsumerisme Baru
Dalam beberapa tahun terakhir, marak fenomena koleksi benda-benda berwujud lucu dan estetik, mulai dari boneka mini, figur dalam blind box, hingga patung vinyl berukuran telapak tangan.Shalom Emmanuel
Tulisan dari Shalom Emmanuel tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Fenomena belanja impulsif blind box lucu: selebrasi estetik, budaya FOMO, atau gejala konsumerisme?
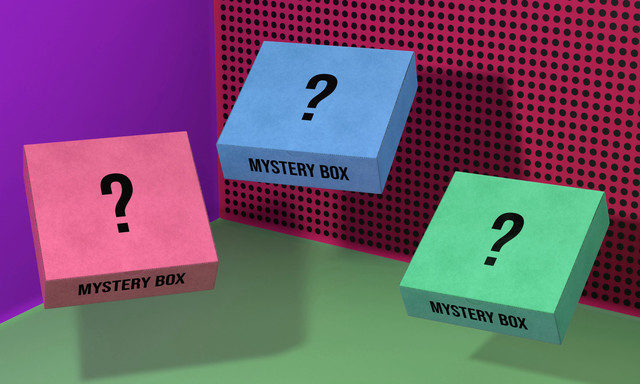
Dalam beberapa tahun terakhir, marak fenomena koleksi benda-benda berwujud lucu dan estetik, mulai dari boneka mini, figur dalam kotak buta (blind box), hingga patung vinyl berukuran telapak tangan yang dibanderol dengan harga fantastis. Meskipun ukurannya kecil dan fungsinya minim, daya tariknya sangat besar. Di media sosial, konten unboxing blind box semakin ramai. Platform seperti TikTok dan Instagram dipenuhi video orang membuka kotak dan bereaksi ketika mendapatkan “rarest item”. Tak jarang, ekspresi senang, kecewa, atau bahkan marah ditunjukkan secara dramatis demi menarik engagement. Konten semacam ini cepat viral karena mudah memancing rasa penasaran dan emosi. Tapi di balik euforia itu, kita perlu bertanya: apa yang sebenarnya sedang kita selebrasikan? Kenapa kita bisa begitu terikat secara emosional dengan benda-benda kecil ini?
Sebagai individu yang hidup dalam budaya visual yang sangat kuat, saya memahami betul betapa menggemaskannya produk-produk ini. Warna pastel, karakter lucu, ekspresi wajah yang dirancang untuk memicu simpati, semua terasa seperti terapi visual. Namun, di balik estetika dan sensasi “healing” yang ditawarkan, saya juga mulai bertanya: apakah ini sekadar hobi, ataukah bentuk konsumsi yang terjebak dalam fenomena budaya yang lebih besar? Apakah kita membeli karena kita menyukainya, atau karena takut ketinggalan tren? Di titik inilah kita perlu merenung lebih jauh.
Koleksi Sebagai Representasi Identitas dan Budaya Pop
Dalam dunia antropologi, benda-benda bukan sekadar objek, melainkan representasi budaya dan identitas. Daniel Miller, seorang antropolog terkemuka dalam kajian benda dan konsumerisme, menyebut bahwa “we are what we consume”. Produk yang kita pilih untuk dikoleksi sering kali mencerminkan nilai, gaya hidup, bahkan aspirasi sosial kita. Figur lucu seperti dari brand L atau C tidak hanya menjadi pemanis ruangan, tapi juga menandakan selera estetik, afiliasi kelas menengah urban, dan pemahaman atas budaya populer global. Tak jarang, orang membeli bukan untuk dinikmati pribadi, melainkan untuk diunggah di Instagram sebagai bentuk aktualisasi diri.
Lebih jauh, praktik koleksi ini juga mengadopsi narasi yang sangat kapitalistik. Ada sistem kelangkaan buatan (artificial scarcity) dalam produksi. Misalnya, satu dari sepuluh blind box memiliki “rare” item. Ini mendorong pembeli untuk membeli lebih dari satu, bahkan banyak, demi mengejar figur langka. Dalam dunia sosiologi konsumsi, ini disebut dengan istilah “planned obsolescence” dan “artificial scarcity”, yang berfungsi menciptakan siklus konsumsi terus-menerus. Dalam kasus ini, unsur kejutan menjadi komoditas utama, mirip dengan model loot box dalam gim daring, yang juga menuai kontroversi karena kemiripannya dengan praktik perjudian ringan.
Konsumerisme, FOMO, dan Rasa Kekosongan yang Terbungkus Estetika
Fenomena ini juga tidak lepas dari budaya FOMO (fear of missing out) yang kuat. Blind box diluncurkan dalam edisi terbatas, sering kali hanya tersedia di periode atau toko tertentu. Sebuah karakter bisa viral hanya dalam semalam, dan jika kita tidak ikut tren itu, kita merasa tertinggal. Ini diperparah oleh media sosial, yang menjadikan hobi koleksi ini bukan lagi ruang pribadi, tapi pertunjukan sosial. Kita mulai merasa tidak cukup hanya memiliki satu; kita merasa harus memiliki semua. Yang semula hobi menyenangkan menjadi obsesi konsumtif. Bahkan dalam beberapa kasus, netizen saling menyalahkan karena ‘reseller’ menaikkan harga, tanpa menyadari bahwa mekanisme kelangkaan dan antusiasme berlebihan-lah yang memperbesar permintaan.
Dalam artikel “Consumerism and Cultural Identity” oleh Chaney (1996), dijelaskan bahwa budaya konsumsi modern tidak hanya menciptakan keinginan, tetapi juga membentuk identitas. Dalam konteks ini, figur koleksi menjadi bagian dari cara seseorang membangun narasi dirinya: imut, berkelas, edgy, atau artsy. Namun ketika koleksi menjadi ajang untuk menambal kekosongan emosional atau status sosial yang rapuh, kita patut berhati-hati. Dalam kajian antropologi psikologis, konsumsi yang terlalu emosional bisa menjadi pelarian dari tekanan sosial atau eksistensial, bukan untuk menikmati benda, tapi untuk menghindari diri sendiri.
Antropologi Barang Lucu: Apakah Kita Sedang Menjadi Subjek atau Objek?
Hal menarik lainnya adalah bagaimana produk-produk ini memperlihatkan dominasi budaya luar. Mayoritas brand figur lucu ini berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Estetika “kawaii” atau “healing” yang mereka tawarkan sangat resonan di kalangan generasi muda Indonesia. Ini menjadi refleksi tentang bagaimana budaya visual Asia Timur, melalui media, hiburan, hingga produk, memengaruhi gaya hidup masyarakat urban Indonesia. Bukan berarti buruk, tapi hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah kita sedang menciptakan budaya sendiri, atau sedang menjiplak estetika budaya lain demi validasi?
Pierre Bourdieu, dalam teorinya tentang “cultural capital”, menyebut bahwa selera itu bukan netral; ia dibentuk oleh kelas sosial dan kekuasaan budaya. Figur-figur koleksi ini, meski tampak netral, sebenarnya tersemat nilai-nilai tertentu: feminin tapi premium, childish tapi sophisticated, lucu tapi limited. Ini menciptakan batasan implisit: siapa yang bisa menjadi kolektor sejati, dan siapa yang hanya bisa mengagumi dari jauh.
Refleksi: Membeli Tidak Salah, Tapi Sadarlah Mengapa
Esai ini tidak ditulis untuk menghakimi mereka yang gemar mengoleksi. Namun saya merasa penting untuk memberi ruang pada kesadaran kritis, bahwa konsumsi adalah tindakan budaya, bukan sekadar ekonomi. Bahwa di balik unboxing blind box, ada narasi kapitalisme yang sedang bekerja. Bahwa koleksi imut bisa menjadi pelarian, tapi juga bisa menjadi perangkap.
Mungkin pertanyaannya bukan lagi “Apa kamu beli Labubu edisi terbaru?” tapi “Kenapa kamu merasa harus beli?” Jika jawabannya karena suka, oke-lah. Tapi jika karena takut tertinggal, karena ingin dianggap punya selera, atau karena merasa hidup butuh distraksi terus-menerus, maka mungkin kita sedang dalam jebakan budaya konsumsi yang manis di luar, namun bisa getir di dalam.
Akhir kata, mari tetap menikmati estetika, tapi jangan menyerahkan diri sepenuhnya pada logika pasar. Koleksi bisa jadi cara berekspresi, tapi jangan sampai kita justru menjadi koleksi dari sistem yang sedang menertawakan kita dari balik rak-rak etalase yang berkilau.

