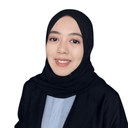Konten dari Pengguna
Masihkan Kita Mendengar Suara Sudan?
12 November 2025 18:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Masihkan Kita Mendengar Suara Sudan?
Sudan kembali menjadi sorotan dunia setelah laporan pembunuhan massal oleh pasukan RSF di El-Fasher. Tragedi ini memperlihatkan betapa lemahnya respons global terhadap genosida dan krisis kemanusiaan Wahyu Wulandari
Tulisan dari Wahyu Wulandari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Belum reda luka kemanusiaan di Palestina, dunia kembali diguncang tragedi memilukan dari Sudan. Apa yang terjadi di negeri Afrika Timur Laut itu sejatinya menampar nurani kita semua. Bagaimana tidak? Kita kembali disuguhi pemandangan pembantaian massal, penghancuran kota, hingga jutaan warga sipil yang terpaksa mengungsi demi menyelamatkan nyawa.
Namun, pertanyaan mendasarnya, mengapa semua ini terjadi, dan mengapa dunia tampak bungkam?
Sudan sendiri merupakan salah satu negara terluas di Afrika, mencakup wilayah sekitar 1,9 juta km persegi. Mayoritas penduduknya beragam Islam, dengan Bahasa resmi Arab dan Inggris. Letak wilayah Sudan cukup strategis, berbatasan dengan tujuh negara serta dilalui oleh sungai nil. Hal ini tentu menjadikan Sudan memiliki nilai geopolitik yang menarik di mata kekuatan asing.
Konflik bersenjata yang kini meluluhlantakan Sudan memuncak tepatnya pada 15 April 2023 di Ibu Kota Khartoum, lalu menyebar ke berbagai wilayah seperti Darfur, Kordofan dan Gezira. Konflik ini disinyalir berakar dari perebutan kekuasaan antara dua kelompok militer: Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), dan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), komandan Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF).
Dikatakan pada awalnya, keduanya pernah berdiri di kubu yang sama. Setelah berhasil menggulingkan rezim Omar al-Bahsir pada 2019, SAF dan RSF berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Namun janji tersebut tak pernah ditepati. Perbedaan kepentingan, ambisi pribadi dan perebutan sumber daya menjadi pemicu yang pada akhirnya menyulut perang terbuka. Titik krusialnya kemudian muncul ketika rencana integrasi RSF ke dalam militer nasional menimbulkan pertentangan, yakni siapa yang berhak memimpin kekuatan bersenjata baru tersebut?
Perbedaan yang semakin meluas akhirnya menimbulkan bentrokan bersenjata yang dimulai pada April 2023, menewaskan lebih dari 150.000 orang dan memaksa 12 juta warga lainnya mengungsi. Keduanya bentrok dalam usaha perebutan wilayah hingga banyak mengorbkan warga sipil. Bahkan disebutkan bahwa peristiwa ini merupakan salah satu tragedy kemanusiaan terburuk abad 21.
Laporan terbaru dari Humanitarian Research Lab (HRL) Universitas Yale mengungkapkan bukti kuat yang menunjukkan adanya dugaan pembunuhan massal oleh Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) setelah kelompok tersebut merebut kota El-Fasher, Darfur Utara. Temuan ini diperoleh melalui analisis citra satelit dan data sumber terbuka yang dikumpulkan pada 27 Oktober 2025.
Menurut HRL Yale, citra satelit menunjukkan kendaraan RSF dikerahkan dalam formasi taktis yang menyerupai operasi penyisiran dari rumah ke rumah di kawasan Daraja Oula, wilayah yang sebelumnya menjadi tempat berlindung warga sipil. Analisis menunjukkan adanya objek-objek di tanah yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia di sekitar kendaraan RSF, disertai perubahan warna tanah kemerahan yang diduga sebagai bekas darah.
Operasi ini berlangsung hanya sekitar 250 meter dari Masjid Al Safiya, tempat RSF sebelumnya melakukan serangan drone pada 19 September 2025 yang menewaskan sekitar 78 orang, dan tidak jauh dari Rumah Sakit Saudi. HRL juga menemukan objek menyerupai tubuh manusia di dekat tembok tanah yang mengelilingi kota El-Fasher, menguatkan laporan adanya eksekusi terhadap warga yang mencoba melarikan diri dari kota.
Sayangnya, sebagaimana disayangkan Direktur WHO, konflik di Sudan nyaris tak mendapat perhatian internasional sebanding dengan krisis di belahan dunia lain. Padahal, penderitaan rakyat Sudan tak kalah nyata dan mungkin jauh lebih sunyi.
Apa yang terjadi di Sudan bukan sekadar perang saudara, tetapi tragedi kemanusiaan yang bisa masuk dalam kategori genosida. Namun, dunia tampak tak terlalu berdaya. Negara-negara besar, yang kerap menyerukan nilai kemanusiaan, justru terjebak dalam politik kepentingan dan selektivitas moral. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun, meski memiliki mandat besar, kerap tak berdaya menghadapi veto politik dan kepentingan ekonomi global yang menjerat setiap upaya penyelesaian konflik.
Tragedi di Sudan menunjukkan bahwa di tengah kemajuan teknologi dan diplomasi global, kemanusiaan masih bisa kalah oleh kekuasaan. Di sisi lain, saya rasa ini juga merupakan PR besar bagi struktur politik internasional dalam menegakkan keadilan universal. Dunia tak boleh berhenti menakar empati berdasarkan kepentingan geopolitik semata, sebab kemanusiaan tentu saja tak memilik paspor. Tidak ada genosida yang pantas diabaikan. Tidak ada tragedi kemanusiaan yang boleh dipilih kasih.