Analisis: Mengapa Israel Doyan Perang?
Sejak berdirinya pada 1948 Israel sudah menjalani berali-kali perang.

Israel adalah negara yang kecanduan perang. Tidak ada penjelasan lain untuk perilaku negara yang telah berperang sejak hari pertama berdirinya ini dan tampaknya tidak memiliki niat untuk hidup damai dengan tetangganya.
Kolumnis Gideon Levy dalam artikel di Haaretz menulis, bahkan ketika tidak ada ancaman langsung terhadap keberadaannya, Israel menemukan cara untuk memicu konflik baru.
Perang adalah oksigennya, raison d'être-nya, dan tanpa perang, Israel seolah kehilangan arah.
Siklus perang Israel dimulai dengan perang yang dianggap "diperlukan" – untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan eksistensi. Lalu, perang yang "diinginkan" muncul, didorong oleh ambisi ekspansionis atau kepentingan politik dalam negeri.
Pengamat politik Marwan Bishara di Aljazeera mengungkapkan, menurut doktrin strategisnya, Israel harus berperang untuk mencapai perdamaian sesuai dengan syaratnya; dan hanya perang, bukan perdamaian, yang dapat menjamin keamanan jangka panjangnya.
Logika pecinta perang
Kecintaan Israel pada perang bersifat rasional dan strategis. Sebagai entitas kolonial, Israel tidak mungkin merdeka tanpa perang. Perang telah digunakan untuk melemahkan musuh-musuhnya dan mempertahankan superioritas militernya atas semua tetangganya. Selain itu, perang-perang Israel membantunya memperluas perbatasan dan menjajah wilayah-wilayah baru.
Menganut logika pecinta perang ini, perdana menteri pertama Israel David Ben Gurion, pernah mengatakan secara terus terang, Israel seharusnya bersedia membayar seorang pemimpin Arab satu juta pound untuk memulai perang dengan negara kolonial yang baru didirikan ini.
Perang untuk Bertahan Hidup

Pada tahun 1948, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan, perang tampak tak terhindarkan. Negara baru itu dikelilingi oleh musuh yang menolak keberadaannya. Perang Kemerdekaan, seperti yang disebut oleh Israel, adalah perang untuk bertahan hidup. Meskipun narasi resmi Israel menggambarkan perang ini sebagai pertempuran heroik melawan kekuatan yang lebih besar, realitasnya lebih kompleks.
Israel memiliki keunggulan militer yang signifikan dibandingkan pasukan Arab yang tidak terkoordinasi, dan konflik itu juga menyebabkan pengusiran massal ratusan ribu warga Palestina – sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba.
Perang 1967, atau Perang Enam Hari, juga sering digambarkan sebagai perang yang "diperlukan". Meskipun Israel menghadapi ancaman nyata dari Mesir, Suriah, dan Yordania, serangan preemptif Israel mengubah konflik menjadi kemenangan gemilang, dengan pendudukan wilayah yang luas: Sinai, Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Namun, kemenangan ini menanamkan benih konflik masa depan, karena pendudukan wilayah-wilayah tersebut menciptakan ketegangan yang belum terselesaikan hingga kini.
Perang-perang ini, setidaknya dalam narasi Israel, kata Gideon Levy, dianggap sebagai perjuangan untuk bertahan hidup. Tetapi bahkan dalam perang yang "diperlukan", ada unsur pilihan. Israel sering kali mempercepat eskalasi, memilih konfrontasi militer daripada diplomasi, seolah-olah perang adalah satu-satunya bahasa yang dipahami.
Perang yang Diinginkan: Ambisi dan Politik
Setelah kemenangan 1967, Israel mulai memulai perang yang tidak sepenuhnya diperlukan, tetapi diinginkan – baik untuk memperluas pengaruhnya maupun untuk memenuhi agenda politik dalam negeri. Perang 1982 di Lebanon adalah contoh klasik. Dijuluki Operasi Damai untuk Galilea, invasi ini bertujuan untuk menghancurkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan membentuk pemerintahan pro-Israel di Lebanon.
Ancaman PLO terhadap Israel pada saat itu minimal, dan perang ini lebih tentang ambisi geopolitik dan keinginan Perdana Menteri Menachem Begin serta Menteri Pertahanan Ariel Sharon untuk membentuk kembali Timur Tengah.
Hasilnya adalah bencana.
Invasi Israel menyebabkan kematian ribuan warga sipil Lebanon, pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila, dan pendudukan Lebanon selatan yang berlangsung selama 18 tahun. Perang ini juga memunculkan Hizbullah, sebuah kekuatan baru yang kini menjadi salah satu musuh paling tangguh Israel. Perang 1982 bukanlah perang untuk bertahan hidup; itu adalah perang yang diinginkan, didorong oleh arogansi dan perhitungan politik yang salah.

Politik sayap kanan
Perang-perang lain yang diinginkan termasuk operasi militer berulang di Gaza, seperti Operasi Cast Lead (2008-2009), Protective Edge (2014), dan berbagai konfrontasi kecil lainnya. Operasi-operasi ini sering dipicu oleh roket dari Hamas atau ketegangan di perbatasan, tetapi eskalasi menjadi perang penuh biasanya merupakan pilihan Israel. Tujuannya sering kali kabur: melemahkan Hamas, menghancurkan infrastruktur militernya, atau sekadar "memotong rumput" – istilah militer Israel untuk menjaga musuh tetap lemah.
Namun, hasilnya selalu sama: kematian massal warga sipil Palestina, kerusakan infrastruktur Gaza, dan ketidakmampuan untuk mencapai solusi politik jangka panjang.
Perang-perang ini juga melayani politik dalam negeri. Pemimpin Israel, dari Ehud Olmert hingga Benjamin Netanyahu, sering menggunakan operasi militer untuk meningkatkan popularitas mereka, mengalihkan perhatian dari skandal korupsi, atau memenuhi tekanan dari basis politik sayap kanan. Perang menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, dan publik Israel, yang telah terbiasa dengan narasi ancaman konstan, sering kali mendukung tindakan keras ini.
Konflik yang Tidak Bisa Dimenangkan
Israel kini terjebak dalam apa yang bisa disebut konflik yang tidak bisa dimenangkan, yang berlarut-larut tanpa akhir yang jelas. Pendudukan Tepi Barat dan blokade Gaza adalah inti dari perang ini. Meskipun tidak selalu melibatkan pertempuran terbuka, pendudukan adalah bentuk perang permanen: pos pemeriksaan, razia malam hari, penahanan tanpa pengadilan, dan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina adalah bagian dari konflik yang terus-menerus.
Perang ini tidak bisa dimenangkan karena tujuannya – mempertahankan kendali atas jutaan warga Palestina tanpa memberikan hak-hak mereka – tidak realistis. Israel tidak bisa menghancurkan aspirasi Palestina untuk kebebasan, tetapi juga tidak bersedia memberikan solusi politik, seperti negara Palestina yang layak. Akibatnya, siklus kekerasan terus berulang: pemberontakan, protes, serangan roket, dan pembalasan Israel.
Hizbullah di Lebanon adalah contoh lain dari konflik yang tak bisa dimenangkan. Perang 2006 melawan Hizbullah berakhir tanpa kemenangan militer yang jelas bagi Israel. Meskipun Israel menghancurkan sebagian besar infrastruktur Lebanon selatan, Hizbullah muncul lebih kuat secara politik dan militer. Hingga hari ini, Israel menghadapi ancaman konstan dari arsenal roket Hezbollah, yang jauh lebih canggih daripada Hamas. Konfrontasi masa depan dengan Hizbullah hampir pasti, tetapi kemenangan militer yang menentukan tampaknya tidak mungkin.
Mengapa Israel Menyukai Perang?

Ada beberapa alasan mengapa Israel tampaknya tidak bisa lepas dari perang. Pertama, militerisme adalah bagian dari identitas nasionalnya. Sejak berdirinya, Israel telah mengandalkan kekuatan militer untuk bertahan hidup di lingkungan yang dianggap bermusuhan.
Angkatan bersenjata Israel (IDF) dianggap sebagai institusi paling suci di negara itu, dan wajib militer memperkuat gagasan bahwa setiap warga adalah prajurit. Dalam budaya ini, solusi militer sering kali diutamakan daripada diplomasi.
Kedua, perang melayani kepentingan politik dan ekonomi. Industri pertahanan Israel adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan ekspor senjata mencapai miliaran dolar setiap tahun. Perang dan ketegangan regional memberikan peluang untuk menguji dan memasarkan teknologi militer, dari sistem pertahanan rudal Iron Dome hingga drone canggih. Selain itu, perang mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri, seperti ketimpangan ekonomi atau ketegangan sosial antara kelompok Yahudi dan Arab di Israel.
Ketiga, narasi ancaman konstan membenarkan kebijakan Israel, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Dengan menggambarkan dirinya sebagai korban yang dikelilingi musuh, Israel memperoleh dukungan dari sekutu seperti Amerika Serikat dan dapat menghindari tekanan untuk menyelesaikan konflik dengan Palestina. Perang memperkuat narasi ini, memungkinkan Israel untuk terus menunda solusi politik.

Jalan Keluar dari Siklus Perang
Apakah Israel bisa keluar dari kecanduan perangnya? Ini adalah pertanyaan sulit, kata Levy. Perdamaian membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir Israel – pengakuan bahwa keamanan sejati tidak dapat dicapai melalui kekuatan militer saja. Ini berarti mengakhiri pendudukan, mengejar solusi dua negara yang adil, dan membangun hubungan dengan tetangga Arab berdasarkan saling menghormati.
Namun, ada hambatan besar. Kepemimpinan politik Israel, khususnya di bawah pemerintahan sayap kanan seperti yang dipimpin oleh Netanyahu, tidak menunjukkan minat pada perdamaian. Publik Israel, yang telah dibentuk oleh dekade-dekade konflik, sering kali skeptis terhadap prospek diplomasi.
Namun, untuk saat ini, Israel tetap terjebak dalam siklus perangnya – perang yang diperlukan, diinginkan, dan mustahil untuk dimenangkan. Hingga Israel memilih untuk memutuskan siklus ini, perang akan terus menjadi bagian dari realitasnya, dengan biaya yang semakin besar bagi semua pihak.



















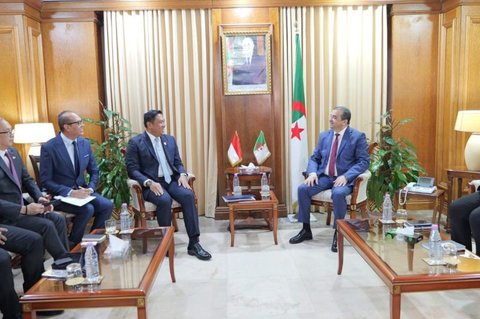

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5480103/original/031715700_1769041871-IMG_5557.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5482815/original/087004900_1769255967-3MJ_1913.JPG)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5482811/original/027935300_1769254413-IMG_7051.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5482788/original/034488500_1769250453-G_a6Q8XbYAAsm42.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5482438/original/071932200_1769206214-Inter_Milan_vs_Pisa_lagi.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5456635/original/096053100_1766912433-david.jpeg)
















